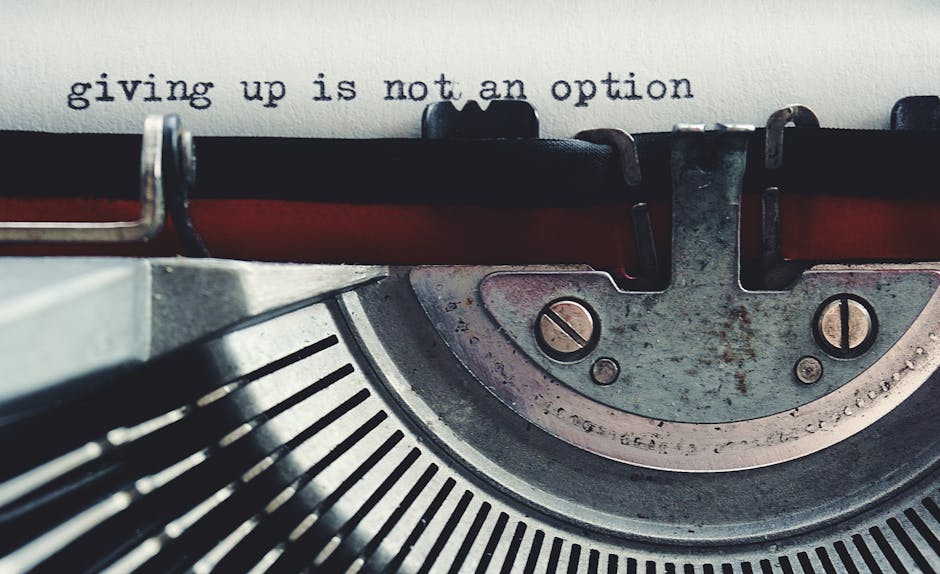Aku selalu membayangkan masa dewasaku akan diwarnai gemerlap cahaya kampus dan tumpukan buku tebal, jauh dari hingar bingar kota kecil tempatku dibesarkan. Rencana itu tersusun rapi, seperti denah bangunan yang kokoh, siap menopang masa depan cemerlang yang telah kurancang sejak lama. Sayangnya, takdir memiliki cetak biru yang jauh lebih rumit, dan ia tak pernah meminta persetujuan kita.
Panggilan telepon mendadak itu merobek peta rencanaku menjadi serpihan. Ayah jatuh sakit, dan toko kayu warisan keluarga yang menjadi satu-satunya sumber penghidupan, kini terancam gulung tikar tanpa tangan yang kuat untuk mengelolanya. Dalam sekejap, ransel yang seharusnya berisi beasiswa ke luar negeri kini digantikan oleh kunci gudang dan tumpukan faktur yang tak kumengerti.
Keputusan untuk tinggal adalah pengorbanan paling menyakitkan yang pernah aku buat; rasanya seperti mencabut akar yang baru saja tumbuh subur. Aku harus melihat teman-temanku terbang tinggi mengejar cita-cita, sementara aku terjebak di antara tumpukan serbuk gergaji dan bau pernis yang menyengat. Ada masanya aku membenci takdir ini, merasa bahwa aku telah dicuri dari masa mudaku yang seharusnya.
Bulan-bulan pertama adalah neraka. Aku naif, mudah ditipu pemasok, dan sering salah menghitung modal. Uang kas terus menipis, dan setiap kegagalan terasa seperti tamparan keras yang membangunkanku dari tidur panjang idealismeku. Aku belajar bahwa dunia nyata tidak peduli dengan nilai akademisku; yang dibutuhkan hanyalah ketahanan dan kemampuan untuk bangkit kembali setelah terjatuh.
Perlahan, aku mulai menemukan ritme yang aneh dalam kekacauan itu. Aku belajar menawar harga tanpa gemetar, memahami karakter para pekerja yang keras kepala namun setia, dan yang terpenting, aku belajar menempatkan kebutuhan orang lain di atas keinginanku sendiri. Kedewasaan ternyata bukanlah pencapaian, melainkan proses panjang penerimaan yang menyakitkan.
Tanggung jawab ini adalah guru terbaikku, sebuah kurikulum intensif yang tidak pernah kutemukan di bangku sekolah mana pun. Melalui perjuangan ini, aku menyadari bahwa seluruh kisah hidupku adalah sebuah narasi epik yang layak disebut Novel kehidupan, di mana setiap babak kegagalan adalah fondasi untuk kekuatan yang baru.
Aku tidak lagi memandang toko kayu ini sebagai penjara, melainkan sebagai medan tempur yang telah membentuk karakterku. Tanganku yang dulu hanya terbiasa memegang pena, kini mahir menggergaji dan merangkai; ada kebanggaan sunyi yang tumbuh dari keringat dan luka lecet. Aku sadar, kedewasaan sejati bukanlah soal usia, melainkan seberapa banyak beban yang mampu kita pikul tanpa menjatuhkan diri.
Malam itu, saat aku menutup pintu toko dan melihat pantulan diriku di kaca, aku melihat seorang pria yang berbeda—lebih lelah, tapi jauh lebih utuh. Meskipun aku kehilangan mimpi yang kurancang, aku mendapatkan diriku yang sebenarnya. Aku telah membayar mahal untuk pelajaran ini, namun harga yang kubayar jauh lebih berharga dari beasiswa manapun.