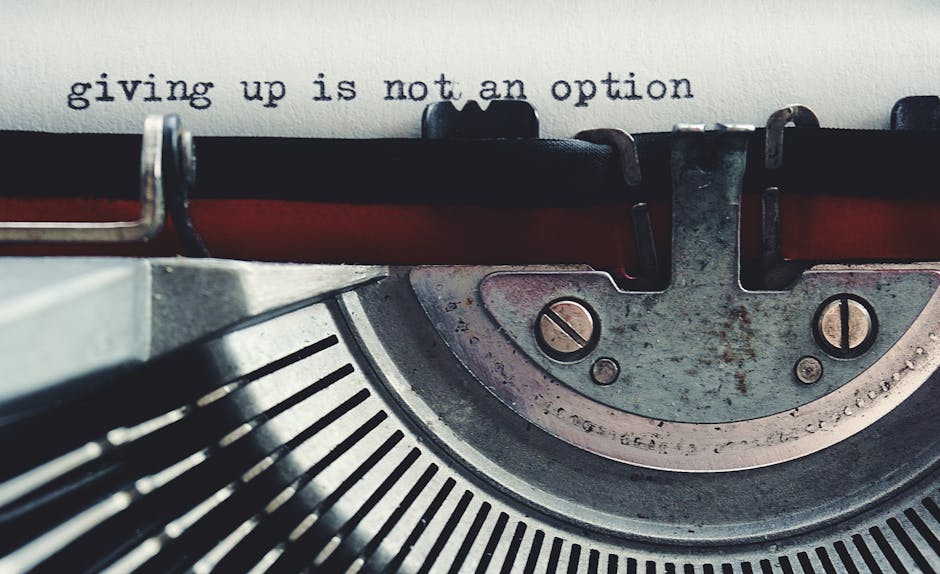Dunia yang kukenal dulu hanyalah labirin buku dan tawa ringan di koridor kampus. Aku adalah Risa, si bungsu yang selalu dilindungi, yang mengira kedewasaan hanyalah tentang mencapai usia legal dan memiliki kartu identitas. Namun, takdir memiliki kurikulum yang jauh lebih keras daripada yang diajarkan di bangku kuliah.
Semua berawal saat Ayah tiba-tiba tumbang, menyerahkan kunci toko buku kecil yang telah menjadi napas keluarga kami selama puluhan tahun. Beban itu datang tanpa ketukan, menuntutku menggantikan peran yang tak pernah kuimpikan; dari mahasiswi menjadi manajer, akuntan, sekaligus pembuat keputusan utama.
Minggu-minggu pertama adalah bencana. Aku keliru menghitung stok, salah memilih pemasok, dan uang kas sering kali tekor karena ketidakmampuanku menawar. Rasa malu dan frustrasi terasa seperti lumpur tebal yang menarikku ke bawah, membuatku ingin kembali bersembunyi di balik selimut dan melupakan semua tanggung jawab ini.
Aku ingat malam saat aku menangis di sudut gudang, mencium aroma kertas tua yang begitu khas. Saat itu, aku hampir mengirim pesan kepada Ibu, mengatakan bahwa aku menyerah, bahwa toko ini harus dijual saja karena aku terlalu lemah untuk memikulnya.
Namun, air mata itu justru membersihkan pandanganku. Aku menyadari bahwa Ayah tidak hanya mewariskan sebuah usaha, melainkan juga sebuah kepercayaan dan kehormatan. Jika aku lari dari tantangan ini, aku tidak hanya mengecewakan mereka, tetapi juga mengkhianati potensi diriku sendiri.
Aku mulai bangkit, memaksa diri bertemu dengan para senior yang lebih berpengalaman, mencatat setiap nasihat, dan menerima kritik pedas dengan lapang dada. Setiap kegagalan yang kualami, setiap tetes keringat yang jatuh saat fajar menyingsing, adalah lembar demi lembar dari Novel kehidupan yang harus kutulis sendiri.
Perlahan, toko itu kembali bernapas. Bukan karena aku hebat, tapi karena aku belajar untuk tidak takut terlihat bodoh dan mau mengakui kesalahan. Kedewasaan ternyata bukanlah pencapaian, melainkan proses panjang penerimaan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana yang kita susun rapi.
Risa yang dulu manja telah mati, digantikan oleh sosok yang lebih kuat, yang memahami bahwa ketahanan mental jauh lebih berharga daripada kenyamanan sesaat. Bekas luka finansial dan emosional yang kudapat kini menjadi medali yang tak terlihat, pengingat bahwa penderitaan adalah guru yang paling jujur.
Aku masih berdiri di ambang pintu toko itu, menatap jalanan yang ramai. Aku mungkin belum meraih kesuksesan besar, tetapi aku telah menemukan diriku yang sejati di tengah badai. Dan kini, pertanyaannya adalah: setelah semua yang kulalui, bisakah aku mempertahankan keteguhan ini saat badai berikutnya datang?