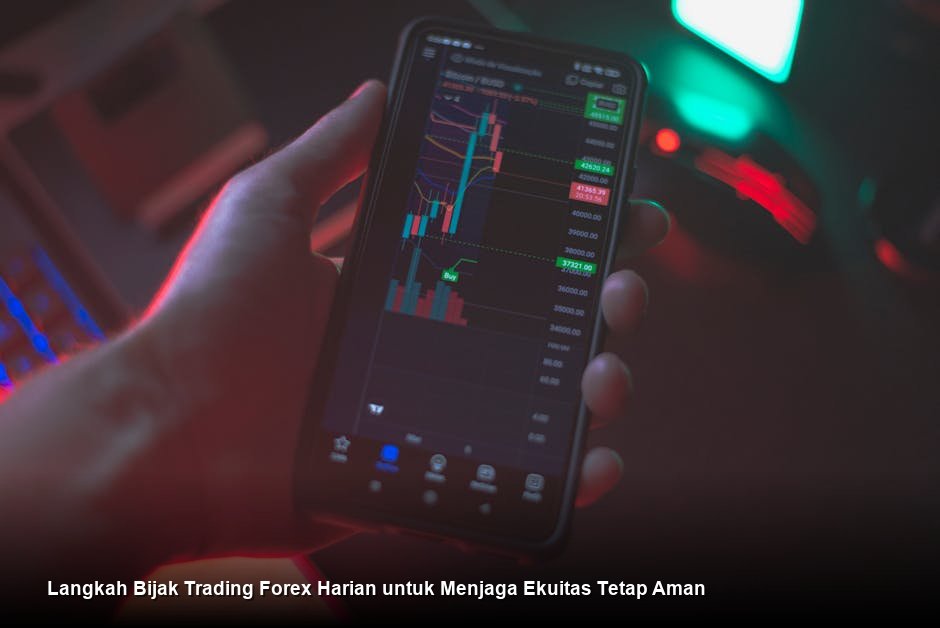Aku selalu membayangkan hidupku seperti lintasan lari yang mulus; lulus, bekerja, lalu mengejar mimpi yang sudah kuukir di dinding kamarku. Dunia bagiku hanyalah rangkaian buku tebal yang harus dilahap, dan kesulitan hanyalah soal ujian yang sulit dipecahkan. Aku naif, bersembunyi di balik ambisi yang terlalu fokus pada diri sendiri.
Namun, semesta punya cara yang brutal untuk menghentikan laju cepatku. Kabar itu datang di suatu sore yang mendung, menyeret seluruh perhatianku dari teori-teori filsafat menuju realitas yang dingin dan keras. Tiba-tiba, aku bukan lagi mahasiswi yang bebas; aku adalah pilar sementara yang harus menopang usaha keluarga yang hampir roboh.
Tanggung jawab itu terasa berat, seperti mantel bulu yang dipaksakan di tengah musim panas. Aku harus berhadapan dengan angka-angka di laporan keuangan, bernegosiasi dengan pemasok, dan menenangkan karyawan yang khawatir. Semua itu jauh lebih rumit daripada soal kalkulus yang pernah membuatku pusing.
Ada malam-malam di mana aku menangis di depan tumpukan faktur, merasa diriku terlalu kecil untuk beban sebesar ini. Aku merindukan kebebasan untuk sekadar membaca novel di bawah pohon, bukan terpaksa menghitung kerugian yang terus menumpuk. Kegagalan terasa begitu nyata, menusuk harga diriku yang selama ini terbang tinggi.
Perlahan, melalui setiap kesalahan kecil dan setiap keberhasilan yang diraih dengan susah payah, aku mulai melihat sesuatu yang baru. Aku belajar bahwa kedewasaan bukanlah tentang usia yang bertambah, melainkan tentang seberapa cepat kita bangkit setelah dihempaskan oleh kenyataan. Aku mulai menghargai proses, bukan hanya hasil akhir.
Pengalaman ini adalah babak yang tak terduga, sebuah skenario yang tidak pernah aku tuliskan dalam buku harian remajaku. Inilah yang disebut Novel kehidupan, di mana plotnya sering kali kejam, namun karakternya dipaksa untuk bertransformasi menjadi versi terbaik dirinya. Aku menyadari, pelajaran terbaik tidak pernah ditemukan di ruang kelas ber-AC, melainkan di tengah panasnya medan perjuangan.
Aku menemukan kekuatan yang tersembunyi di sudut-sudut jiwaku, kekuatan yang hanya muncul ketika keadaan memaksa. Aku belajar berbicara dengan tegas, mengambil keputusan tanpa keraguan, dan yang terpenting, menerima bahwa menunda mimpi bukan berarti menguburnya. Itu hanya jeda, sebuah persiapan mental untuk kembali dengan fondasi yang lebih kuat.
Ketika usaha itu akhirnya stabil, dan aku bisa bernapas lega, aku menatap bayanganku di cermin. Mata itu masih sama, tetapi sorotnya berbeda; lebih tenang, lebih bijaksana, dan penuh penerimaan. Aku tidak lagi melihat seorang gadis yang takut gagal, melainkan seorang wanita yang tahu bagaimana rasanya bertahan.
Maka, jika suatu hari nanti kau merasa takdirmu berbelok tajam dari rencana awal, ingatlah bahwa belokan itu mungkin adalah jalan tercepat menuju kedewasaan sejati. Beranilah menerima jeda semesta itu, karena di sanalah karaktermu yang sesungguhnya sedang ditulis. Kau siap melanjutkan babak berikutnya?