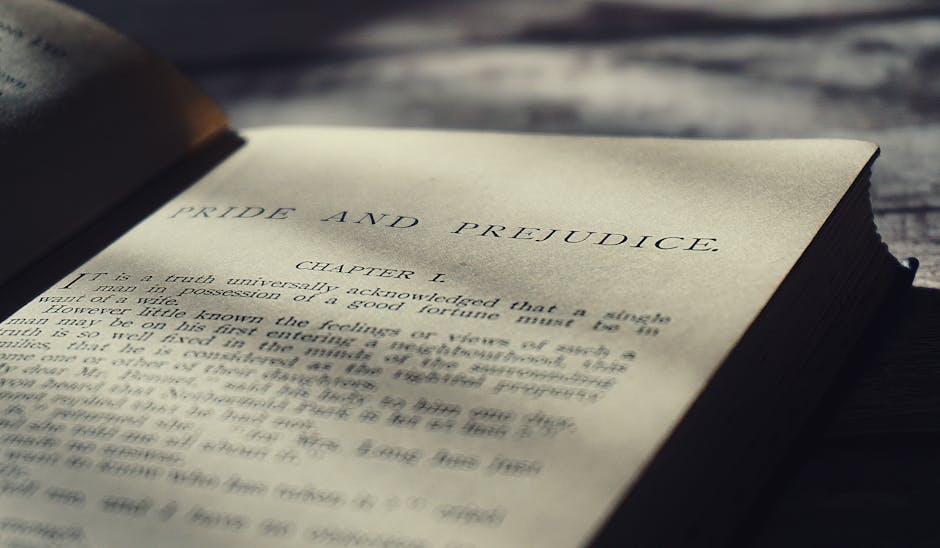Dahulu, hidupku adalah rentetan janji manis yang kubangun sendiri, disusun dari tawa riang dan rencana perjalanan tanpa batas. Aku adalah seorang pemimpi yang percaya bahwa dunia berputar sesuai irama keinginanku, tanpa pernah menyentuh tanah keras bernama kenyataan. Langitku selalu biru, dan aku yakin badai hanyalah cerita fiksi dalam buku.
Namun, badai itu datang tanpa peringatan, bukan dalam bentuk angin kencang, melainkan keheningan yang menyesakkan di ruang tengah. Ayah jatuh sakit, dan bersamaan dengan itu, usaha kecil yang menopang kami ambruk ditelan hutang yang tak terduga. Tiba-tiba, aku, si sulung yang paling manja, harus menanggalkan gaun impianku dan mengenakan seragam tanggung jawab.
Aku ingat malam-malam awal itu, di mana air mata lebih sering menjadi teman daripada tidur. Ada kemarahan yang membakar, mengapa takdir memilihku, orang yang paling tidak siap untuk memikul beban sebesar ini? Aku membenci setiap keputusan yang harus kuambil, setiap pengorbanan kecil yang merenggut sisa-sisa masa mudaku.
Lalu, aku mulai bekerja. Bukan di kantor mewah seperti yang selalu kuimpikan, melainkan di kedai kopi kecil di sudut kota yang ramai. Tangan yang terbiasa memegang pena kini harus cekatan membersihkan meja dan melayani pesanan, sementara pikiran terus menghitung sisa uang untuk biaya pengobatan Ayah.
Proses itu terasa seperti pengamplasan jiwa; sakit, perih, dan melelahkan, namun perlahan membentuk sesuatu yang lebih kuat. Aku belajar bahwa kedewasaan bukanlah tentang usia yang bertambah, melainkan tentang kesediaan untuk berdiri tegak saat semua yang kau cintai mulai runtuh. Aku berhenti menyalahkan takdir dan mulai mencari solusi.
Aku menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi di bawah lapisan keegoisan dan idealisme. Senyum tulus dari Ibu, meski kelelahan, dan tatapan penuh harap dari adik-adikku menjadi bahan bakar yang tak pernah habis. Mereka tidak meminta, tetapi kehadiran mereka menuntutku untuk menjadi jangkar.
Ini adalah bagian terberat dari Novel kehidupan yang harus kutulis; skenario di mana pahlawan harus mengubur sebagian dirinya agar yang lain bisa bertahan. Aku belajar bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan guru yang paling jujur dan keras, yang memaksa kita untuk menyusun ulang prioritas dan definisi kebahagiaan.
Seiring berjalannya waktu, kedai kopi itu tidak lagi terasa sebagai penjara, melainkan sekolah. Aku belajar bernegosiasi, mengelola emosi, dan yang paling penting, menghargai setiap remah kemudahan yang pernah kuterima. Luka-luka itu tidak hilang, tetapi kini menjadi garis-garis tegas yang membentuk karakterku.
Aku mungkin kehilangan beberapa tahun terbaik masa mudaku, namun sebagai gantinya, aku mendapatkan diriku yang sesungguhnya—seseorang yang mampu bertahan dan melindungi. Pertanyaannya, setelah semua badai ini berlalu, apakah aku masih memiliki keberanian untuk kembali bermimpi, ataukah aku akan selamanya terperangkap dalam bayang-bayang tanggung jawab yang baru saja kuciptakan?