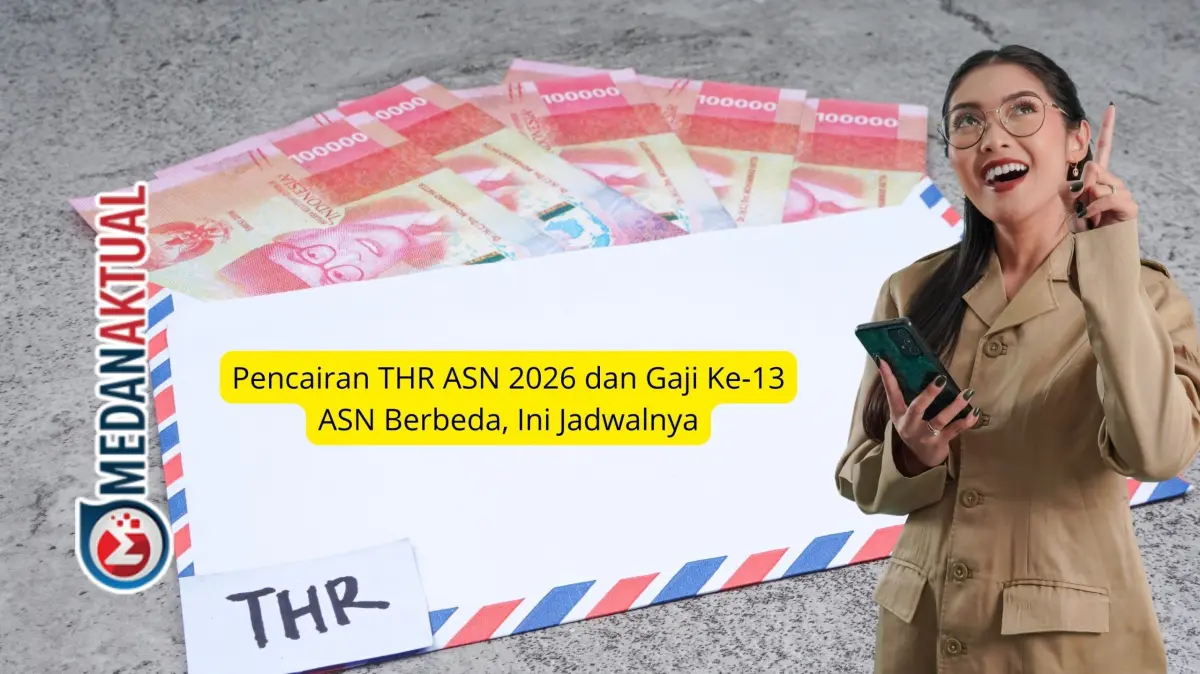Aku selalu membayangkan kedewasaan adalah sebuah pencapaian yang mulus, didapatkan setelah meraih gelar master atau menandatangani kontrak besar pertama. Risa yang berusia dua puluhan itu adalah seorang idealis yang percaya bahwa bakat dan semangat saja sudah cukup untuk membangun dunia. Aku memandang tantangan sebagai permainan yang pasti bisa kumenangkan dengan sedikit usaha ekstra.
Namun, hidup memiliki cara yang brutal untuk merobek ilusi. Patahan pertama datang saat mentor yang kukagumi, sosok yang menjamin seluruh karirku, tiba-tiba harus mundur karena kondisi kesehatan yang kritis. Seluruh beban proyek pembangunan kompleks perumahan terbesar di kota itu, yang saat itu hampir ambruk karena mismanajemen, jatuh ke pundakku.
Kepanikan menelanku utuh. Aku yang biasanya percaya diri, kini duduk di ruang rapat yang dingin, hanya bisa mendengar gema keraguan dari para investor senior. Mereka memandangku, seorang gadis muda dengan kacamata tebal dan ide-ide yang terlalu puitis, seolah aku adalah lelucon yang mahal. Proyek itu bukan hanya tentang tumpukan beton; itu adalah reputasiku, dan lebih penting lagi, masa depan banyak orang.
Malam-malamku berubah menjadi rentetan kopi pahit dan revisi sketsa yang tak berujung. Aku harus belajar cepat bagaimana memimpin tim yang didominasi oleh veteran skeptis, bagaimana bernegosiasi dengan kontraktor yang licik, dan bagaimana menerima fakta bahwa terkadang, solusi terbaik adalah solusi yang paling pragmatis, bukan yang paling indah.
Ada momen ketika aku ingin menyerah, kembali ke kamar kecilku dan berpura-pura tidak pernah mendengar kata "tanggung jawab." Air mata jatuh membasahi denah lantai, mencampur tinta biru dengan rasa frustrasi yang menusuk. Aku menyadari, kedewasaan bukanlah hadiah, melainkan luka yang sembuh dan meninggalkan bekas yang kuat.
Di tengah kekacauan itu, aku mulai memahami bahwa setiap kesulitan adalah babak penting dalam Novel kehidupan yang sedang kutulis. Aku bukan lagi Risa yang hanya tahu cara bermimpi, tetapi Risa yang tahu cara membangun fondasi, bahkan ketika fondasi itu harus dibangun di atas puing-puing kegagalan. Rasa sakit itu bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membentuk tulang punggung yang lebih kokoh.
Aku berhasil. Bukan dengan keajaiban, melainkan dengan keringat, darah, dan keberanian untuk mengakui bahwa aku tidak tahu segalanya, lalu mencari tahu jawabannya. Ketika kompleks itu berdiri tegak, megah, aku tidak merasakan euforia kemenangan, melainkan keheningan yang mendalam.
Aku menatap pantulan diriku di jendela kantor. Wajah itu terlihat lebih lelah, tetapi matanya memancarkan cahaya yang berbeda—cahaya yang ditempa oleh badai. Proyek itu selesai, reputasiku terselamatkan, tetapi yang paling berharga adalah aku telah berhenti mencari validasi eksternal.
Sekarang, aku tahu bahwa pengalaman yang paling menyakitkan adalah guruku yang paling jujur. Lalu, apa lagi yang siap dilemparkan kehidupan padaku? Aku tersenyum, siap menerima tantangan berikutnya, karena aku sudah tahu, jatuh hanyalah permulaan dari babak baru.