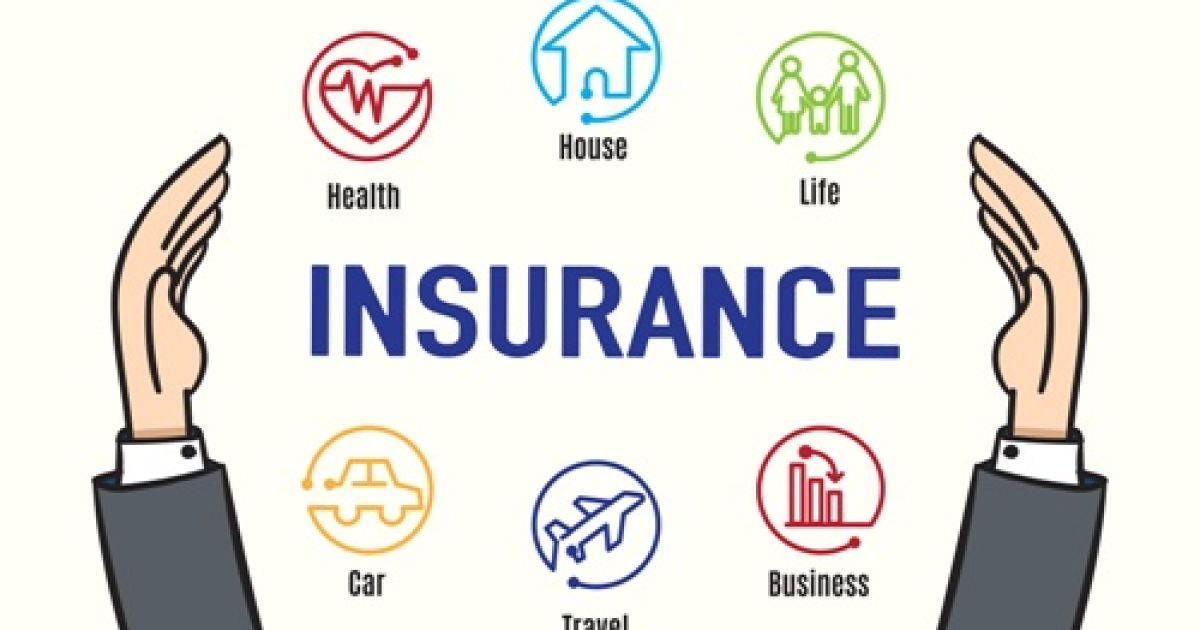Aku ingat jelas, dulu duniaku hanyalah kanvas dan warna cat air yang meluap. Rencana hidupku sudah tersusun rapi: lulus dengan predikat terbaik, lalu terbang ke Eropa mengejar beasiswa seni yang telah lama kuimpikan. Kedewasaan bagiku hanyalah formalitas usia yang akan datang seiring waktu.
Namun, hidup punya skenario sendiri yang jauh lebih dramatis daripada imajinasiku. Tiba-tiba, kabar buruk itu datang bersamaan dengan tumpukan berkas tagihan yang tak terduga. Ayahku ambruk, dan usaha kecil yang menjadi tulang punggung keluarga kini terancam gulung tikar.
Semua mimpi yang kubangun perlahan runtuh, digantikan oleh aroma kertas kuitansi dan bau debu gudang yang asing. Aku, si pemimpi yang hanya tahu cara memadukan warna, kini harus belajar cara memadukan angka dan menghadapi tatapan tajam para kreditor yang menuntut kejelasan. Tanggung jawab itu datang tanpa permisi, memaksaku menanggalkan jubah kemudaanku.
Malam-malamku yang seharusnya dihabiskan untuk merancang komposisi visual, kini berganti menjadi sesi maraton menghitung kerugian dan menyusun strategi. Ada rasa pahit yang menusuk saat aku harus mengirim email penolakan beasiswa itu, membiarkan kesempatan emas itu terbang menjauh tanpa bisa kupegang lagi.
Aku sempat membenci kenyataan ini, merasa Tuhan terlalu kejam merenggut masa depanku. Namun, seiring waktu berjalan, aku mulai menemukan kekuatan aneh yang tersembunyi di balik kelelahan. Aku belajar bernegosiasi, meredam emosi di depan karyawan yang cemas, dan mengambil keputusan sulit yang dampaknya terasa nyata.
Perlahan, aku sadar bahwa proses ini adalah sekolah kehidupan yang paling berharga. Ini adalah **Novel kehidupan** yang tak pernah tertulis di buku-buku kuliah, di mana setiap kegagalan kecil menjadi babak baru yang mengajarkanku ketahanan. Aku mulai melihat dunia bukan dari bingkai idealis yang kuciptakan, melainkan dari sudut pandang pragmatis yang penuh empati.
Aku tidak lagi sekadar Risa si seniman, tetapi Risa si pengambil keputusan, si pemecah masalah. Rasa bangga itu muncul bukan dari pujian atas karya seni, melainkan dari keberhasilan membayar gaji karyawan tepat waktu, atau saat Ayah tersenyum melihat laporan keuangan yang mulai membaik.
Kedewasaan ternyata bukan pencapaian, melainkan proses yang menyakitkan namun mendalam. Ia adalah bekas luka yang terbentuk saat kita dipaksa berdiri tegak, meski badai masih menderu kencang.
Kini, setahun telah berlalu, dan usahaku kembali stabil. Aku masih menyimpan kuas dan kanvas di sudut kamar, tetapi aku tahu, Risa yang sekarang jauh lebih kuat dari Risa yang dulu. Aku telah kehilangan mimpi yang indah, namun sebagai gantinya, aku menemukan diriku yang sejati. Lalu, ketika sebuah surat tak terduga tiba di meja kerjaku, membawa tawaran baru yang mustahil untuk diabaikan, aku tahu babak perjuangan ini belum benar-benar usai, melainkan baru saja dimulai dengan versi diriku yang jauh lebih siap.