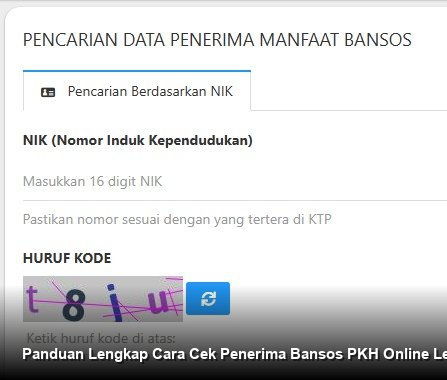Aku selalu percaya bahwa kedewasaan adalah sinonim dari kesempurnaan dan kontrol mutlak. Di usia muda, aku sudah mengenakan jubah kesombongan, yakin bahwa setiap langkah yang kuambil, setiap keputusan yang kubuat, adalah kalkulasi tanpa cela. Aku memandang kegagalan sebagai aib, bukan sebagai guru, sehingga aku tanpa sadar mendorong siapa pun yang mencoba menawarkan kritik atau bantuan tulus.
Proyek ambisius jembatan kota, yang kuanggap sebagai mahakarya pribadiku, menjadi panggung utama bagi kejatuhanku. Aku mengabaikan peringatan dari tim teknik senior mengenai kelemahan fundamental pada desain fondasi, terlalu yakin bahwa kecerdasanku akan mengatasi hukum fisika. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa berdiri sendiri, tanpa campur tangan siapa pun.
Tepat di malam presentasi akhir, ketika hujan deras mengguyur, simulasi digital proyek itu runtuh di hadapan para investor. Bukan hanya fondasi yang gagal; egoku yang rapuh pun ikut hancur berkeping-keping di depan mata semua orang. Keheningan yang mengikuti kekacauan itu terasa lebih mematikan daripada gemuruh kegagalan itu sendiri.
Minggu-minggu berikutnya adalah masa isolasi total, di mana cahaya matahari terasa asing dan aku hanya bisa melihat pantulan diriku yang penuh rasa malu. Aku menyadari bahwa kesuksesan yang kubangun selama ini hanyalah menara pasir yang menunggu gelombang pasang. Aku kehilangan peta yang selama ini kupedomani, dan tiba-tiba, aku tidak tahu lagi siapa aku tanpa predikat ‘jenius’ yang melekat.
Di tengah kekosongan itu, Pak Seno, mentor lamaku yang pernah kutinggalkan, datang tanpa menghakimi. Ia hanya berkata bahwa hidup bukanlah serangkaian cetak biru yang harus sempurna, melainkan sebuah proses adaptasi yang brutal namun indah. Ia menyebutnya sebagai babak paling esensial dalam sebuah Novel kehidupan, di mana karakter utama harus jatuh sejatuh-jatuhnya untuk bisa menulis ulang takdirnya.
Mendengarkan perkataannya, aku mulai mengerti. Kedewasaan bukanlah tentang seberapa tinggi aku bisa terbang, melainkan seberapa tangguh aku saat jatuh, dan seberapa cepat aku belajar untuk meminta uluran tangan. Aku mulai memunguti puing-puing kegagalan, menyadari bahwa setiap retakan yang ada kini bisa menjadi jalan masuk bagi empati dan kerendahan hati.
Aku menghubungi kembali timku, meminta maaf atas arogansiku, dan mulai bekerja dari nol. Kali ini, bukan lagi tentang membuktikan diri sebagai yang terbaik, melainkan tentang membangun sesuatu yang benar-benar kokoh, bersama-sama. Aku belajar bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kontrol, melainkan pada kolaborasi dan kemampuan untuk menjadi rentan.
Pengalaman itu tidak hanya mengubah karierku, tetapi juga jiwaku. Aku tidak lagi takut pada kegagalan, sebab aku tahu bahwa setiap luka adalah penanda bahwa aku telah berjuang, telah merasakan, dan yang terpenting, telah tumbuh. Kedewasaan bukanlah tujuan yang dicapai, melainkan proses berkelanjutan yang hanya bisa diukur dari kedalaman hati, bukan dari tingginya pencapaian.
Kini, aku berdiri di tepi jurang yang sama, tapi pandanganku jauh berbeda. Aku tahu, badai pasti akan datang lagi. Pertanyaannya bukan apakah aku akan jatuh, melainkan: ketika aku jatuh nanti, apakah aku akan bangkit sebagai orang yang sama, atau sebagai seseorang yang jauh lebih bijaksana dan manusiawi?