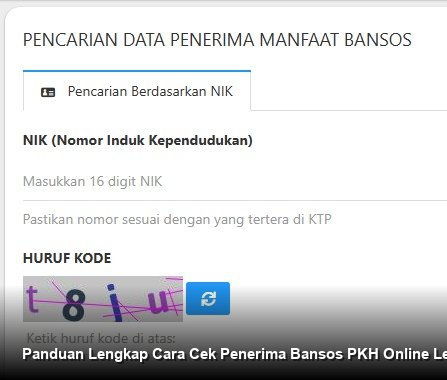Aku selalu membayangkan kedewasaan adalah sebuah pintu gerbang yang dilewati dengan anggun, setelah menamatkan pendidikan tinggi dan mendapat pekerjaan mapan. Kenyataannya, kedewasaan datang seperti badai mendadak, meruntuhkan semua dinding kaca pelindung yang kubangun sejak kecil. Semua bermula ketika Ayah jatuh sakit, dan tiba-tiba saja, tanggung jawab mengurus galeri seni keluarga yang sedang sekarat itu jatuh sepenuhnya di pundakku.
Dunia yang tadinya penuh teori dan idealisme di bangku kuliah, kini berubah menjadi medan perang akuntansi dan negosiasi yang dingin. Aku harus berhadapan dengan tumpukan tagihan yang menggunung dan karyawan yang mulai kehilangan kepercayaan. Setiap keputusan kecil terasa seperti mempertaruhkan masa depan, dan aku seringkali pulang dengan kepala pening dan hati yang remuk karena rasa tidak mampu.
Pukulan terberat datang bukan dari kesulitan finansial, melainkan dari pengkhianatan. Aku memercayai seorang rekan lama yang seharusnya membantuku mengelola inventaris, namun ia justru memanfaatkan situasi genting ini untuk keuntungan pribadinya. Rasa dikhianati itu lebih menyakitkan daripada melihat angka kerugian di laporan bulanan, membuatku mempertanyakan setiap niat baik yang pernah kutabur.
Malam itu, di tengah kegelapan galeri yang sunyi, aku menangis bukan karena lelah, melainkan karena kesadaran pahit. Aku menyadari bahwa orang dewasa tidak selalu tahu apa yang mereka lakukan; mereka hanya terus bergerak maju meskipun takut. Aku harus berhenti mencari figur penyelamat dan mulai menerima bahwa akulah satu-satunya nakhoda di kapal yang sedang karam ini.
Inilah kurikulum paling brutal dan paling jujur yang pernah kualami. Setiap air mata, setiap kegagalan negosiasi, dan setiap kali aku harus menelan harga diri demi mencari solusi, semuanya adalah babak penting dalam Novel kehidupan yang sedang kutulis. Aku belajar bahwa kepahitan adalah bumbu wajib yang membuat rasa syukur menjadi lebih manis.
Perlahan, aku mulai berdiri tegak. Aku belajar memaafkan—bukan hanya rekan yang mengkhianatiku, tetapi juga diriku sendiri atas kesalahan-kesalahan bodoh yang kubuat. Aku menemukan kekuatan tak terduga dalam diri, sebuah cadangan energi yang hanya muncul ketika semua opsi lain telah habis.
Aku mulai melihat galeri itu bukan lagi sebagai beban, melainkan sebagai warisan yang harus diperjuangkan dengan darah dan air mata. Aku mengubah strategi, merangkul seniman lokal, dan bahkan mulai menjual kopi di sudut galeri untuk menarik pengunjung baru. Perlahan, lampu-lampu galeri mulai bersinar kembali, bukan karena keajaiban, melainkan karena ketekunan yang keras kepala.
Kedewasaan ternyata bukan tentang mencapai target, melainkan tentang kemampuan bangkit setelah terjatuh berulang kali tanpa kehilangan esensi diri. Pengalaman pahit itu mencetakku menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih bijak, dan yang terpenting, lebih manusiawi.
Kini, aku tak lagi takut pada kegagalan; aku justru takut jika tidak mencoba. Tapi ada satu hal yang masih menghantuiku: apakah Ayah akan sempat melihat keberhasilan yang kuperjuangkan ini, ataukah aku akan selamanya membawa beban bahwa aku terlambat?