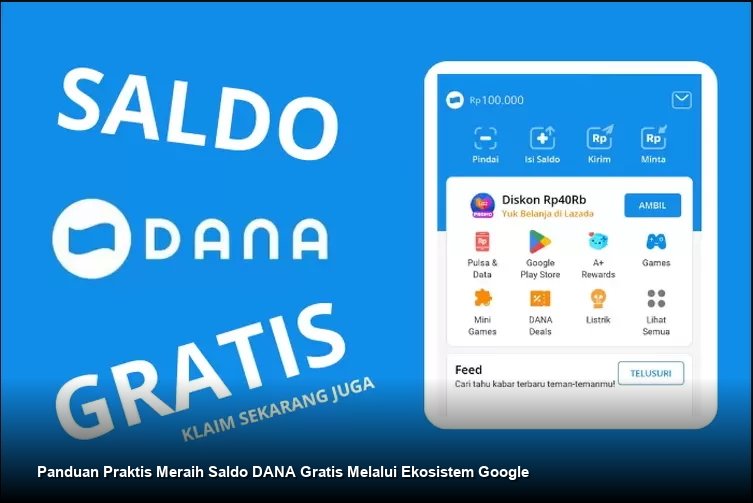Dahulu, aku mengira kedewasaan adalah tentang mencapai target finansial atau memegang jabatan tinggi di usia muda. Aku berjalan dengan langkah penuh percaya diri, atau lebih tepatnya, kesombongan, yakin bahwa bakat alamiahku akan selalu menjadi perisai dari segala bentuk kegagalan. Keyakinan itu rapuh, seperti kaca yang menunggu benturan keras.
Benturan itu datang saat proyek desain terbesar dalam karierku hancur berantakan. Bukan karena kurangnya ide, melainkan karena aku menolak mendengarkan peringatan tim dan bersikeras bahwa intuisiku tak pernah salah. Kerugian yang ditimbulkan bukan hanya materi, tetapi juga hilangnya kepercayaan dari orang-orang yang paling kuhormati.
Untuk pertama kalinya, aku merasakan pahitnya kegagalan yang mutlak, yang tidak bisa ditutupi oleh alasan apa pun. Aku menarik diri dari keramaian kota, mencari perlindungan di balik dinding kamar yang sunyi, mencoba memproses gemuruh kekecewaan yang menyerbu relung hati. Masa-masa itu adalah lembah paling gelap, tempat aku harus menghadapi bayangan diriku yang paling arogan.
Ayahku, seorang pria yang selalu berbicara lewat tindakan, hanya memberiku satu nasihat singkat, “Kegagalan bukanlah akhir dari jalan, Nak. Itu adalah belokan tajam yang menuntutmu untuk berjalan lebih lambat dan melihat sekeliling.” Kata-kata itu menancap, perlahan mengubah rasa malu menjadi tekad untuk memperbaiki, bukan menutupi.
Aku mulai dari nol, kembali pada dasar-dasar yang dulu kusepelekan, belajar disiplin dan ketelitian. Proses ini sunyi dan melelahkan, jauh dari sorotan dan tepuk tangan yang dulu selalu kucari. Aku menyadari bahwa kematangan sejati tidak diukur dari seberapa cepat kita mencapai puncak, tetapi seberapa gigih kita bangkit setelah terjerembab.
Perjalanan ini adalah halaman yang harus kubaca berulang kali, babak paling krusial dalam Novel kehidupan yang sedang kutulis. Setiap kritik pedas kini kuanggap sebagai pupuk, bukan racun; setiap kesulitan adalah kesempatan untuk menguji seberapa kuat fondasi yang telah kubangun. Aku berhenti mencari validasi eksternal dan mulai fokus pada integritas diri.
Setahun kemudian, kesempatan itu kembali datang, proyek yang serupa, dengan taruhan yang jauh lebih besar. Kali ini, aku tidak lagi memimpin dengan ego, melainkan dengan kolaborasi dan kerendahan hati. Aku menerima masukan, merangkul ketidakpastian, dan bekerja dengan kesadaran penuh bahwa hasil terbaik lahir dari proses yang jujur.
Kedewasaan bukanlah capaian, melainkan sikap—kesediaan untuk bertanggung jawab penuh atas setiap pilihan, baik yang menghasilkan kemenangan maupun yang berujung pada kehancuran. Kini, ketika aku melihat pantulan diriku, aku melihat seseorang yang pernah jatuh, namun berhasil menambal retakan itu dengan emas kearifan. Apakah aku akan berhasil memenangkan proyek ini, atau kembali merasakan pahitnya kekalahan? Aku tidak tahu, tetapi yang pasti, aku sudah menang atas diriku yang lama.