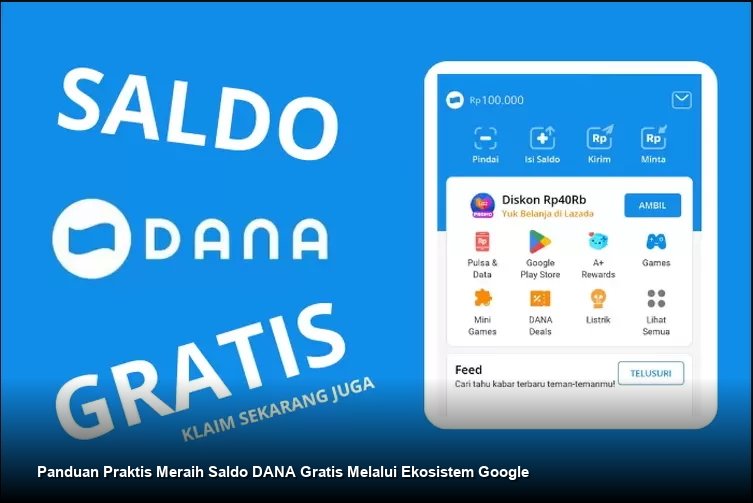Dulu, hidupku adalah kanvas kosong yang siap diisi dengan warna-warna cerah Paris, tempat aku berencana mengejar sekolah seni impian. Aku hidup dalam gelembung kenyamanan yang indah, percaya bahwa masa depan hanyalah garis lurus menuju kebahagiaan yang telah direncanakan. Kedewasaan hanyalah label usia yang akan kuterima pada waktunya, bukan sebuah medan perang.
Namun, takdir punya sketsa yang berbeda. Pagi itu, kabar buruk tentang kesehatan Ayah dan kondisi bengkel batik keluarga yang terancam gulung tikar merobek peta perjalananku menjadi serpihan kecil. Tiba-tiba, tas ransel yang semula berisi perlengkapan sketsa kini harus diganti dengan tumpukan faktur dan laporan keuangan yang memusingkan.
Keputusan itu berat, pahit, dan menusuk: aku harus menunda keberangkianku, mungkin selamanya, dan mengambil alih kendali bengkel yang selama ini hanya kukenal sebagai tempat bermain masa kecil. Beban tanggung jawab yang tiba-tiba menimpa pundakku terasa seperti jubah besi yang terlalu berat untuk dikenakan oleh seorang gadis berusia dua puluhan. Aku harus belajar membedakan sutra terbaik dan menghadapi tatapan skeptis para karyawan senior.
Malam-malamku yang seharusnya dihabiskan untuk melukis, kini berganti dengan hitungan rugi-laba dan negosiasi dengan para pemasok yang menuntut pembayaran. Ada saatnya aku menangis di balik tumpukan kain mori, merindukan kebebasan yang telah kutinggalkan. Rasa frustrasi itu seringkali membisikkan agar aku menyerah saja, kembali menjadi Risa yang hanya tahu cara bermimpi.
Aku ingat betul suatu sore, ketika aku menemukan buku sketsa lama yang penuh dengan coretan desain mode. Melihat gambar-gambar itu membuatku sadar; kedewasaan bukanlah tentang berapa banyak lilin yang kau tiup, melainkan seberapa kuat kau berdiri tegak saat badai menerpa. Itu adalah proses metamorfosis yang menyakitkan, mengubah ulat manja menjadi kupu-kupu yang sayapnya penuh bekas luka.
Perlahan, aku mulai menemukan ritme baru. Aku menyadari bahwa seni tidak harus selalu berada di galeri; ia bisa hidup di setiap helai benang batik yang kuselamatkan. Dengan tangan gemetar, aku mulai menggabungkan visi seniku dengan tradisi keluarga, menciptakan motif baru yang membawa harapan bagi bengkel tua itu.
Semua pengalaman pahit dan manis ini, kegagalan dan kemenangan kecil yang kuraih, telah menjadi babak penting. Aku menyadari bahwa apa yang sedang kujalani ini adalah Novel kehidupan yang sesungguhnya; penuh plot twist tak terduga, karakter yang menguji kesabaran, dan konflik yang harus diselesaikan tanpa bantuan editor.
Meskipun bekas luka pengorbanan itu masih terasa, ia kini tidak lagi menjadi penghalang, melainkan pengingat akan kekuatanku. Aku belajar bahwa mengorbankan mimpi demi kewajiban bukanlah akhir, melainkan sebuah jalan memutar yang justru memperkaya jiwa dan memperkuat akar.
Lalu, di tengah kesibukanku menyusun pola baru, sebuah surat dari sekolah seni di luar negeri tiba di meja kerjaku. Mereka menawarkan beasiswa penuh, sebuah kesempatan yang telah lama kulepaskan, dengan catatan: kesempatan itu harus diambil dalam tiga bulan ke depan. Haruskah aku memilih kembali pada mimpi lama, atau tetap memeluk tanggung jawab yang telah mematangkanku?