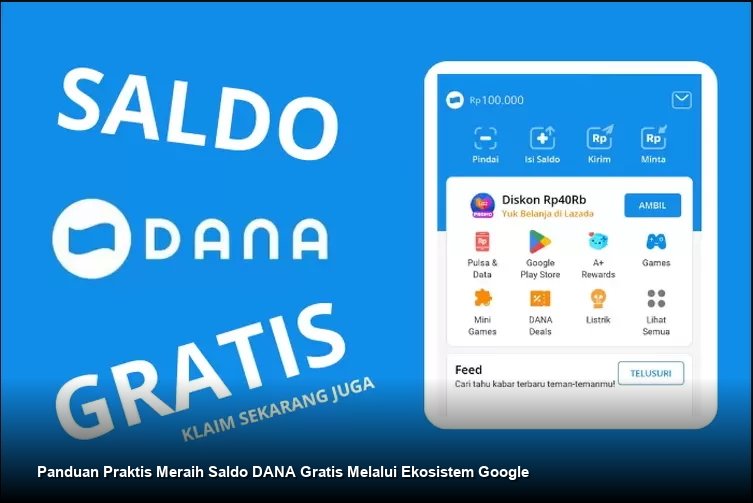Aku selalu percaya bahwa hidupku akan berjalan lurus, mulus, dan berakhir sesuai dengan cetak biru yang kususun sejak remaja. Kepercayaan diri itu adalah perisai sekaligus kelemahan terbesarku, sampai pada hari ketika notifikasi kegagalan itu muncul di layar, meruntuhkan seluruh fondasi yang kubangun selama bertahun-tahun. Seketika, aku bukan lagi si jenius muda yang dielu-elukan, melainkan hanya seorang gadis yang tersesat dalam reruntuhan ekspektasinya sendiri.
Rasa malu yang menusuk lebih tajam daripada penolakan itu sendiri. Aku menghabiskan beberapa minggu hanya memandangi langit-langit kamar, merasa seperti boneka yang talinya diputus, tak tahu bagaimana cara bergerak lagi. Dunia luar terasa terlalu bising, terlalu menghakimi, dan aku memilih memenjarakan diri dalam keheningan yang dingin.
Namun, keheningan itu perlahan mulai berbicara. Ia menyadarkanku bahwa kedewasaan bukanlah tentang meraih kesuksesan gemilang, melainkan tentang bagaimana kita bangkit setelah terhempas ke titik paling dasar. Aku harus melepaskan citra diriku yang sempurna dan mengakui bahwa aku hanyalah manusia biasa yang rentan, yang perlu belajar dari setiap kesalahan.
Ayah, yang biasanya keras dan menuntut, justru menunjukkan sisi lembutnya. Ia tidak memberiku solusi, tetapi memberiku ruang untuk bernapas dan memunguti pecahan-pecahanku sendiri. Tatapan kecewa yang kukhawatirkan justru berganti menjadi tatapan penuh pengertian, seolah ia berkata, "Inilah hidup, Nak, dan kamu harus melaluinya." Aku memutuskan untuk kembali bekerja, bukan pada bidang impianku, melainkan pada pekerjaan sederhana yang menuntut ketekunan dan kerendahan hati. Setiap tugas kecil yang kuselesaikan, setiap sen yang kuperoleh dari keringatku sendiri, terasa jauh lebih berharga daripada semua pujian yang pernah kuterima di masa lalu. Aku belajar tentang nilai waktu, tentang empati, dan tentang betapa sulitnya orang-orang di luar sana berjuang setiap hari.
Ini adalah babak paling jujur dalam Novel kehidupan yang selama ini kujalani. Aku menyadari bahwa cerita yang bagus tidak pernah hanya berisi kebahagiaan; ia harus memiliki konflik, pengorbanan, dan momen-momen gelap yang memaksa karakter utama untuk berevolusi. Aku mulai menulis ulang alur ceritaku, menggunakan tinta yang terbuat dari air mata dan tekad yang membara.
Bekas luka yang ditinggalkan oleh kegagalan itu kini bukan lagi sumber rasa malu, melainkan peta yang menunjukkan seberapa jauh aku telah melangkah. Aku telah menemukan kekuatan yang tidak pernah kukira kumiliki, sebuah ketahanan yang hanya bisa ditempa oleh api kesulitan. Aku bukan lagi Risa yang naif; aku adalah Risa yang utuh, yang memahami bahwa jatuh adalah bagian dari proses terbang.
Lalu, sebuah kesempatan tak terduga datang—sebuah jalan baru yang sama sekali tidak pernah kuprediksi. Apakah ini takdir yang memberiku kesempatan kedua, atau ujian lain yang lebih berat? Aku menatap cermin, melihat pantulan mata yang kini lebih tajam dan siap, bertanya-tanya, apakah aku benar-benar siap menghadapi babak selanjutnya yang menanti di balik pintu itu?