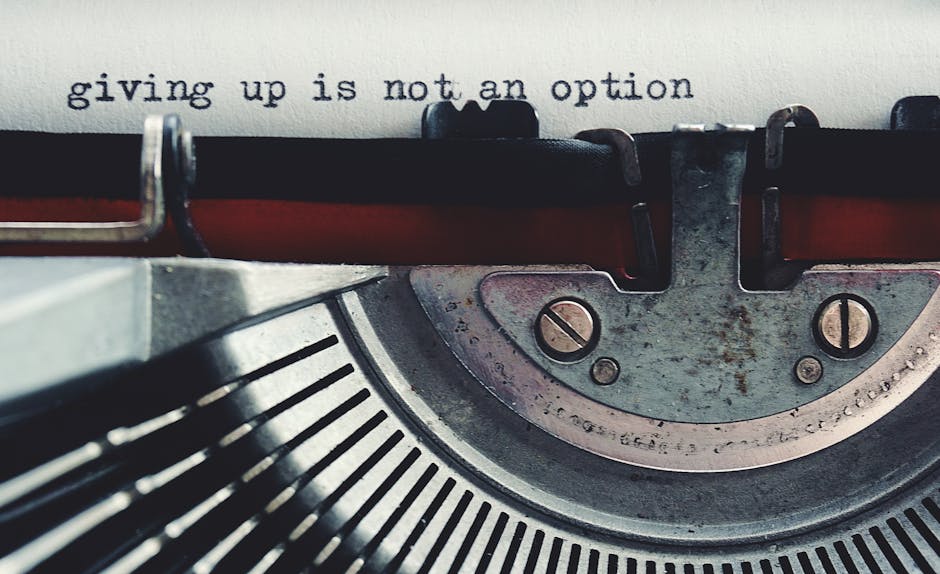Aku ingat sekali aroma bandara yang dingin, bercampur dengan harapan yang menguap. Tiket ke benua seberang sudah ada di tangan, beasiswa penuh yang kuperjuangkan sejak SMP, namun kakiku terpaku di garis batas imigrasi. Aku tahu, jika aku melangkah maju, aku akan meninggalkan diriku yang lama, tetapi juga meninggalkan semua yang kurasa wajib kulindungi.
Keputusan itu datang mendadak, secepat kabar bahwa Ayah ambruk dan usaha batik keluarga di ambang kehancuran. Mimpi-mimpi indah tentang studi di luar negeri luruh seketika, digantikan oleh bau malam yang pekat dan aroma lilin panas di bengkel tua. Rasa marah dan kecewa sempat menjadi teman tidurku, mempertanyakan mengapa takdir sekejam ini merenggut masa depanku.
Sejak saat itu, hari-hariku diisi oleh hitungan rugi-laba, negosiasi yang keras, dan tatapan skeptis dari para pekerja senior. Aku, si gadis kutu buku yang hanya fasih membahas teori ekonomi makro, kini harus berhadapan langsung dengan tumpukan kain yang gagal dicelup dan tagihan yang menumpuk. Setiap malam adalah perjuangan untuk menahan air mata dan mencari solusi di tengah kekacauan.
Puncak keputusasaan terjadi saat kami kehilangan pesanan terbesar karena keterlambatan produksi. Aku duduk di antara gulungan kain yang berantakan, merasakan beban seluruh warisan keluarga menindih pundakku yang kurus. Saat itu, aku menyadari bahwa kedewasaan bukanlah soal usia, melainkan tentang kemampuan berdiri tegak setelah badai menerjang.
Perlahan, aku mulai belajar. Bukan hanya belajar bagaimana mengelola keuangan, tetapi belajar memahami manusia—memahami ketakutan para pekerja yang bergantung padaku, dan memahami ketulusan Ayah yang mempertaruhkan segalanya. Aku membaca buku manajemen hingga subuh, mengubah pola pikir dari seorang pemimpi menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab.
Aku menyadari bahwa semua ujian berat ini adalah babak paling penting dalam Novel kehidupan yang sedang aku jalani. Setiap kegagalan adalah alinea yang menguatkan, dan setiap solusi yang kutemukan adalah titik balik narasi. Aku tidak lagi melihat bengkel ini sebagai penjara, melainkan sebagai medan tempur yang membentuk karakterku.
Meskipun bekas luka kehilangan mimpiku masih terasa, ada kebanggaan baru yang tumbuh saat melihat desain batik baruku diterima pasar dengan baik. Keberhasilan kecil itu jauh lebih manis daripada nilai A sempurna di mata kuliah yang kukagumi dulu. Aku telah menemukan diriku yang baru, yang lebih tangguh dan berempati.
Maturitas memang harus dibayar mahal, seringkali dengan pengorbanan yang tak terhitung harganya. Aku mungkin tidak mendapatkan gelar dari universitas impianku, tetapi aku mendapatkan gelar yang jauh lebih berharga: gelar sebagai individu yang mampu menopang kehidupan orang lain.
Lantas, bagaimana jika suatu hari nanti, kesempatan beasiswa itu datang lagi, mengetuk pintu yang kini sudah kukunci rapat demi tanggung jawab? Apakah aku akan memilih kembali pada mimpi lama, ataukah aku akan tetap berdiri teguh, menjaga api warisan yang telah kubangun dengan air mata dan keringat ini?