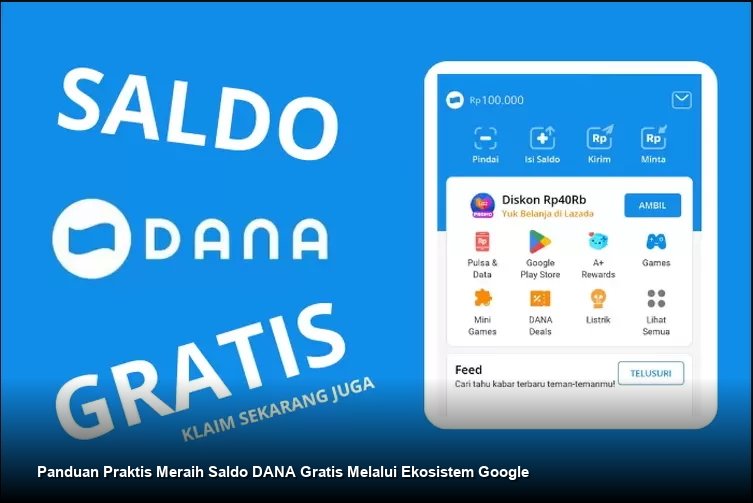Dulu, aku percaya bahwa kedewasaan adalah garis finis yang dicapai setelah melewati usia tertentu, seolah-olah waktu secara otomatis akan memberikan kebijaksanaan. Aku memulai proyek sosial ambisius dengan dada membusung penuh keyakinan, menganggap bahwa semangat saja sudah cukup untuk membangun sebuah harapan. Aku tidak melihat lubang di fondasi rencana, terlalu silau oleh kilauan visi yang kubayangkan.
Proyek "Mercusuar Ilmu" adalah segalanya bagiku, janji yang kuberikan kepada warga desa terpencil yang mendambakan akses pendidikan. Aku menggalang dana, mengerahkan relawan, dan memimpin dengan arogansi seorang jenderal muda yang belum pernah mencicipi kekalahan. Aku menolak saran untuk memperlambat laju, yakin bahwa kecepatan adalah kunci kesuksesan.
Tentu saja, semesta punya cara tersendiri untuk mengoreksi kesombongan. Tiga bulan setelah peletakan batu pertama, saat hujan deras mengguyur tanpa henti, struktur utama bangunan itu ambruk—bukan karena cuaca, melainkan karena perhitungan teknis yang aku abaikan. Suara gemuruh itu bukan hanya merobohkan dinding, tapi juga meremukkan harga diriku menjadi serpihan debu.
Rasa malu yang menusuk lebih dalam daripada kritik tajam mana pun. Aku menghilang selama berminggu-minggu, mengunci diri di kamar seolah-olah kegagalan ini adalah penyakit menular yang harus kusembunyikan dari dunia. Aku merasa aku telah merampas harapan, dan beban kekecewaan yang terpancar dari mata warga desa terasa seperti rantai besi yang melilit leherku.
Namun, di tengah kegelapan itu, muncul kesadaran yang dingin dan jernih: lari bukanlah pilihan. Inilah bagian terberat dari proses pendewasaan, saat kita dipaksa menghadapi diri sendiri yang paling rentan dan paling gagal. Aku menyadari bahwa skenario hidupku ini adalah bagian penting dari sebuah Novel kehidupan, di mana setiap babak pahit harus diselesaikan, bukan dirobek.
Aku kembali ke desa, bukan dengan janji-janji muluk, melainkan dengan sepasang tangan yang siap bekerja membersihkan puing. Aku meminta maaf, mengakui setiap kesalahan, dan yang paling mengejutkan, mereka menerima penyesalanku tanpa penghakiman. Mereka hanya meminta satu hal: keberanian untuk memulai lagi, bersama-sama.
Proses pembangunan kembali memakan waktu dua kali lipat dari rencana awal, tapi kali ini, setiap batu diletakkan dengan kehati-hatian, setiap keputusan didiskusikan dengan kerendahan hati. Aku belajar bahwa kepemimpinan sejati bukanlah tentang memberi perintah, melainkan tentang mendengarkan dan mengakui keterbatasan diri.
Bekas luka kegagalan itu tidak pernah hilang; ia terukir dalam ingatanku sebagai peta yang menunjukkan jalan yang tidak boleh kuambil lagi. Kedewasaan bukanlah tentang tidak pernah jatuh, melainkan tentang bagaimana kita memilih untuk bangkit—dengan punggung yang lebih tegak dan pandangan yang lebih rendah hati.
Kini, Mercusuar Ilmu berdiri kokoh, bukan hanya sebagai bangunan, tapi sebagai monumen pengingat bahwa kegagalan adalah guru yang paling jujur. Namun, di balik senyumku saat peresmian, aku tahu tantangan yang sebenarnya baru saja dimulai. Apakah aku benar-benar siap menggunakan kedewasaan yang baru kuperoleh ini untuk menghadapi badai berikutnya, badai yang mungkin jauh lebih besar dan lebih pribadi?