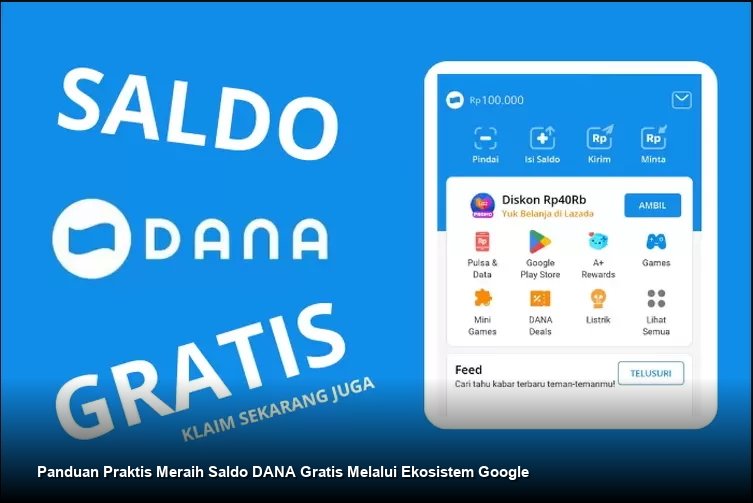Mimpiku saat itu adalah menembus batas langit, mengejar beasiswa master di benua seberang. Semua persiapan sudah matang, koper sudah hampir terisi, dan masa depan terasa begitu berkilauan dalam imajinasiku. Namun, hidup memiliki skenario yang jauh lebih rumit daripada yang kutulis di buku harian.
Panggilan telepon larut malam itu merobek segalanya, mengubah peta perjalananku menjadi puing-puing tak berbentuk. Ayah sakit, bisnis keluarga goyah, dan tiba-tiba saja aku harus memilih antara ambisi pribadi dan tanggung jawab yang tak terucapkan. Aku merasa seperti ditenggelamkan, dipaksa berenang di lautan yang belum pernah kukenal.
Awalnya, ada rasa marah yang mendidih; mengapa aku, mengapa sekarang, setelah semua pengorbanan itu? Aku menghabiskan malam-malamku dengan menatap tiket pesawat yang kini tak lagi berarti, meratapi hilangnya kesempatan yang mungkin takkan datang dua kali. Kedewasaan terasa seperti beban berat yang dipaksakan, bukan anugerah yang dinanti.
Tapi, air mata tidak membayar tagihan. Aku memutuskan untuk memutar haluan, memanfaatkan keahlian kecil yang kumiliki—meracik kopi dan mengelola komunitas lokal. Dari studio kecil di sudut rumah, aku memulai usaha, belajar membaca neraca keuangan yang selama ini kuhindari.
Pengalaman ini mengajarkanku bahwa teori dan praktik adalah dua entitas yang sangat berbeda. Ketika seorang karyawan melakukan kesalahan fatal, aku harus menelan kekecewaan dan belajar mengelola emosi, bukan hanya angka. Di titik inilah aku menyadari bahwa setiap babak sulit dalam hidup adalah bagian krusial dari Novel kehidupan yang sedang kita tulis.
Aku mulai memahami arti sebenarnya dari empati, bukan hanya sekadar kata-kata manis yang kubaca di buku motivasi. Mengurus orang lain, menanggung risiko, dan memastikan roda kehidupan terus berputar, semua itu mengikis lapisan ego yang selama ini melindungiku. Bekas luka kegagalan dan kelelahan justru menjadi ukiran yang memperindah jiwaku.
Perlahan, usaha kecilku mulai menghasilkan buah, bukan dalam bentuk kemewahan, melainkan dalam bentuk ketenangan batin. Aku tidak lagi mengejar validasi dari gelar akademis yang tinggi, tetapi dari kemampuan untuk bertahan dan memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitarku. Rasa bangga itu jauh lebih tulus dan membumi.
Jika dulu kedewasaan bagiku adalah mencapai target usia tertentu, kini aku tahu itu adalah kemampuan untuk menerima ketidakpastian dengan kepala tegak. Aku belajar bahwa kehilangan rencana BUKANLAH akhir, melainkan awal dari penemuan diri yang paling otentik.
Aku mungkin kehilangan mimpi lamaku, tapi aku mendapatkan diriku yang baru—seorang yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap. Pertanyaannya, setelah semua ini, apakah aku benar-benar siap untuk menghadapi babak berikutnya yang pasti akan jauh lebih menantang?