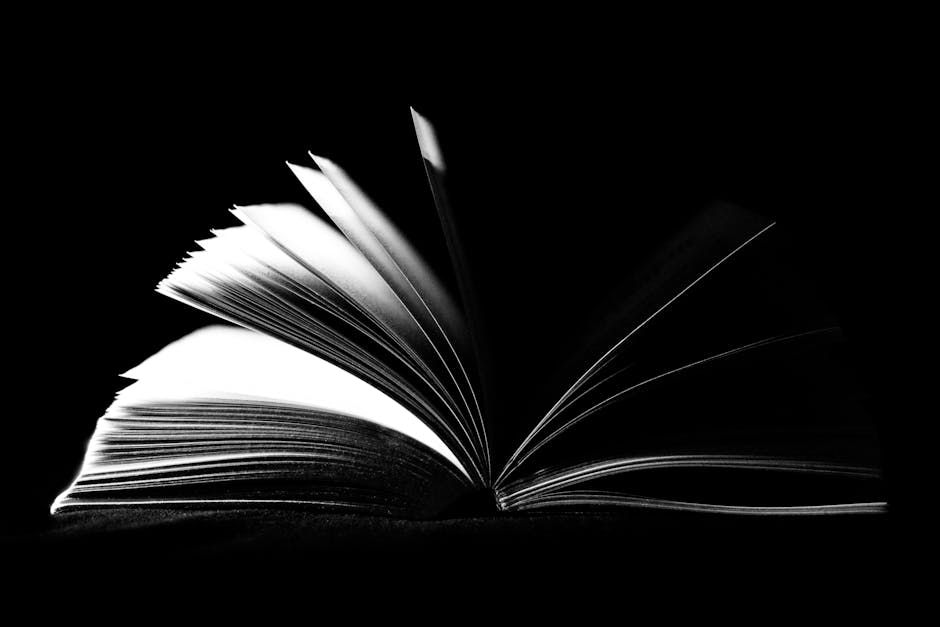Aku ingat sekali, rencanaku sudah terpetakan sempurna: studi arsitektur di Milan, sketsa-sketsa yang siap menembus batas langit, dan kebebasan yang terasa di ujung jari. Koper cokelatku bahkan sudah tergeletak di sudut kamar, menunggu hari keberangkatan yang seharusnya menjadi gerbang menuju masa depan impian. Namun, takdir memiliki cetak biru yang jauh lebih rumit dari yang kubayangkan.
Satu panggilan telepon di tengah malam mengubah segalanya, merobek peta impian itu menjadi serpihan tak berarti. Ayah jatuh sakit, dan bisnis kerajinan kayu yang menjadi tulang punggung keluarga mendadak limbung tanpa nahkoda. Di usia yang baru saja menyentuh angka dua puluh, aku dihadapkan pada pilihan yang terasa kejam: mengejar ambisi atau memikul beban yang mendadak terasa berat di pundak.
Aku memilih tinggal, membiarkan beasiswa emas itu terlepas seperti debu yang tertiup angin. Rasa pahit pengorbanan itu bukan hanya terasa di lidah, tetapi menusuk relung hati setiap kali aku melihat tiket pesawat yang tak terpakai. Aku harus belajar cepat membaca laporan keuangan, bernegosiasi dengan pemasok yang curang, dan menghadapi karyawan yang meragukan kepemimpinanku.
Malam-malamku kini dihabiskan di gudang yang berbau serbuk kayu, bukan di perpustakaan yang harum buku. Ada hari-hari ketika aku ingin menyerah, berteriak pada semesta karena merasa dicuri dari masa mudaku. Tapi setiap aku melihat wajah lelah Ibu dan tatapan penuh harap Ayah, aku tahu bahwa keberanian sejati adalah bertahan, bukan melarikan diri.
Proses itu adalah tempaan yang brutal namun jujur. Kedewasaan ternyata bukan soal usia, melainkan seberapa jauh kita mampu merangkul kekacauan tanpa kehilangan pijakan. Aku mulai mengerti bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan data berharga untuk langkah berikutnya, dan bahwa empati jauh lebih sulit dipraktikkan daripada teori yang kubaca di bangku sekolah.
Setiap transaksi yang berhasil, setiap senja yang kulewati sambil membereskan tumpukan kayu, terasa seperti babak baru yang harus kulewati. Aku menyadari bahwa ini adalah bagian terpenting dari Novel kehidupan yang sedang kutulis; sebuah kisah tentang pengorbanan yang justru memberiku identitas yang lebih kuat.
Aku tidak lagi memandang bisnis ini sebagai beban, melainkan sebagai warisan, sebagai janji yang harus kutepati. Aku mulai menemukan keindahan dalam detail kecil: serat kayu yang unik, senyum tulus dari pelanggan lama, dan rasa bangga saat melihat produk kami kembali diminati pasar.
Mungkin aku kehilangan kesempatan untuk melihat Duomo dari dekat, tetapi aku mendapatkan pemandangan yang jauh lebih berharga: kekuatan dan ketahanan keluargaku sendiri. Kedewasaan yang kudapatkan ini adalah mahar yang mahal, dibayar dengan air mata dan keringat, namun menjadikanku manusia yang utuh.
Maka, ketika kini aku berdiri di ambang pintu gudang, menatap langit malam yang tenang, aku tidak lagi merasakan penyesalan. Aku tahu, impian yang tertunda tidak hilang, ia hanya sedang beristirahat. Pertanyaannya sekarang, setelah semua badai ini berlalu, apakah aku masih akan menjadi Arka yang sama saat tiba waktunya untuk kembali merangkai mimpi yang sempat kuhentikan?