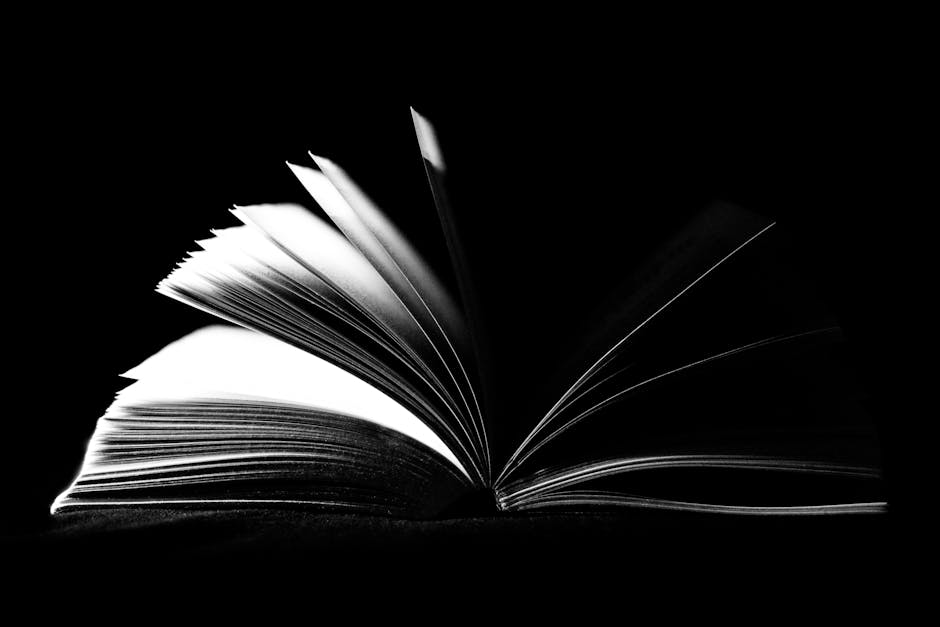Aku selalu berpikir bahwa kedewasaan akan datang perlahan, seiring dengan bertambahnya koleksi lukisan dan pameran seni yang berhasil kugelar. Dinding kamarku dipenuhi sketsa impian, kanvas-kanvas tebal yang menunggu sentuhan warna paling berani. Dunia bagiku adalah galeri yang luas, dan aku adalah seniman yang bebas menentukan paletnya.
Namun, palet itu tiba-tiba dirampas oleh kenyataan yang keras dan berdebu. Suatu sore, kabar buruk tentang toko kerajinan ayah menghantam rumah kami seperti badai tak terduga, merobek lapisan perlindungan yang selama ini kurasakan. Ayah terdiam, matanya yang biasanya penuh semangat kini hanya menyimpan kelelahan dan rasa bersalah yang mendalam.
Aku ingat betul bau cat minyak yang menguap dari studio kecilku ketika aku mengambil keputusan. Dengan tangan gemetar, aku mengemas semua kuas dan pigmen, menyimpannya dalam peti kayu di sudut gudang. Itu bukan hanya sekadar menyimpan alat, melainkan mengubur sementara versi diriku yang paling dicintai dan bebas.
Minggu-minggu pertama adalah neraka. Aku harus belajar membaca laporan keuangan yang rumit, bernegosiasi dengan pemasok yang wajahnya selalu masam, dan menghadapi tumpukan tagihan yang tak pernah habis. Aku yang biasa melukis pemandangan indah, kini harus berhadapan dengan angka-angka merah yang terasa mencekik.
Ada satu malam, ketika aku duduk sendirian di balik meja kasir yang dingin, aku menyadari betapa naifnya aku selama ini. Aku melihat bayangan Ayah dan Ibu dalam setiap garis kerutan di kertas bon lama, memahami pengorbanan sunyi yang mereka lakukan agar aku bisa mengejar mimpi. Kedewasaan ternyata bukan tentang mencapai impian, melainkan tentang menopang fondasi agar orang yang kita cintai tidak roboh.
Perlahan, aku mulai menemukan ritme baru. Aku belajar bahwa ketelitian dalam menghitung laba-rugi juga membutuhkan kreativitas, sama seperti mencampur warna. Aku menyadari bahwa perjalanan ini adalah sebuah babak baru dalam Novel kehidupan yang tak bisa kupilih alurnya, tetapi harus kutulis dengan sepenuh hati.
Setiap transaksi yang berhasil, setiap senja yang kulewati sambil membereskan rak-rak toko, memberikan pelajaran berharga yang tak pernah kudapatkan di bangku kuliah seni. Aku belajar sabar, belajar bertanggung jawab, dan yang terpenting, belajar untuk tidak lari dari badai. Aku tumbuh bukan karena aku ingin, melainkan karena keadaan memaksaku untuk menjadi tiang bagi keluarga.
Mungkin, peti kayu berisi kuas itu akan tetap di sana untuk waktu yang lama. Tapi kini, ketika aku menatap pantulan diriku di jendela toko, aku melihat seseorang yang berbeda—seseorang yang lebih kuat dan lebih tenang. Aku tahu, suatu hari nanti aku akan kembali melukis, tetapi kali ini, kanvasku akan jauh lebih kaya, diwarnai oleh pengalaman pahit dan manis yang membentuk jiwa.