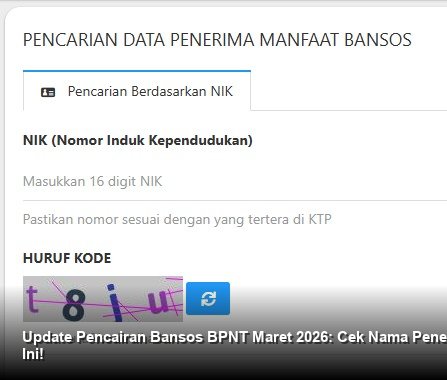Aku selalu percaya bahwa hidupku akan menjadi narasi agung yang ditulis dengan tinta emas pencapaian. Namun, saat surat penolakan dari universitas impian itu tiba, seluruh cetak biru masa depanku hancur berkeping-keping, meninggalkan aku terdampar di jurang kehampaan yang dingin. Kesombongan yang selama ini aku pelihara perlahan menguap, digantikan oleh rasa malu yang menusuk.
Beberapa bulan setelahnya, aku menerima pekerjaan yang jauh dari citra diri yang selama ini aku bangun: menjadi asisten di sebuah panti jompo kecil di pinggiran kota. Ini adalah tempat yang sunyi, di mana waktu bergerak lambat, dan setiap sudutnya dipenuhi bau minyak kayu putih dan kisah-kisah masa lalu yang terlupakan. Aku merasa seolah aku telah melangkah mundur, terperangkap dalam jeda yang tidak aku inginkan.
Di sana aku bertemu dengan Kakek Bimo, seorang mantan guru sejarah yang kini hanya bisa duduk di kursi roda. Ia tidak pernah memberiku nasihat yang bombastis, melainkan hanya pertanyaan-pertanyaan sederhana yang memaksa aku melihat ke dalam diri: “Apa yang kamu cari, Nak? Gelar, atau makna?” Awalnya, aku menjawab dengan sinis, masih berpegangan pada idealisme bahwa kegagalan ini hanyalah kecelakaan sementara. Namun, menyaksikan Kakek Bimo menghadapi rasa sakitnya dengan senyuman tulus setiap pagi, membuat getar keraguan mulai merayap dalam keyakinanku. Aku mulai menyadari bahwa kesuksesan yang aku kejar hanyalah kulit luar; kedewasaan adalah tentang bagaimana kita merespons ketika kulit itu terkelupas.
Panti jompo itu, yang semula aku anggap sebagai penjara, perlahan berubah menjadi sekolah kehidupan yang paling jujur. Aku belajar mendengarkan tanpa menghakimi, merawat tanpa mengharapkan imbalan, dan menemukan keindahan dalam rutinitas yang monoton. Ini adalah babak tergelap, tetapi juga yang paling mencerahkan.
Aku mulai membaca kembali kisah-kisah orang-orang yang aku rawat, menyadari bahwa setiap kerutan di wajah mereka adalah peta perjalanan yang kompleks dan penuh liku. Kegagalan, kehilangan, dan kebahagiaan—semua terjalin menjadi satu. Inilah esensi dari Novel kehidupan, di mana plot terbaik sering kali ditemukan di luar skenario yang kita tulis sendiri.
Perlahan, aku tidak lagi berfokus pada pintu yang tertutup, melainkan pada jendela kecil yang terbuka di hadapanku. Aku mulai menulis kisah mereka, menemukan bahwa empati jauh lebih berharga daripada semua pujian akademik yang pernah aku dapatkan. Kegagalan itu telah memaksaku berhenti berlari dan mulai menanam akar.
Kedewasaan ternyata bukan tentang mencapai puncak, melainkan tentang membangun fondasi yang kuat di lembah. Aku belajar bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk mengakui kerapuhan diri dan tetap berdiri tegak, meskipun mahkota kebanggaan sudah lama jatuh ke tanah.
Malam itu, saat Kakek Bimo menggenggam tanganku yang dingin, ia hanya berbisik, “Jangan takut pada akhir dari sebuah bab, Risa. Karena setiap akhir adalah kesempatan untuk menuliskan prolog yang lebih bijaksana.” Aku mengangguk, menyadari bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan kegagalan kemarin adalah bekal yang paling berharga untuk esok yang belum tertulis.