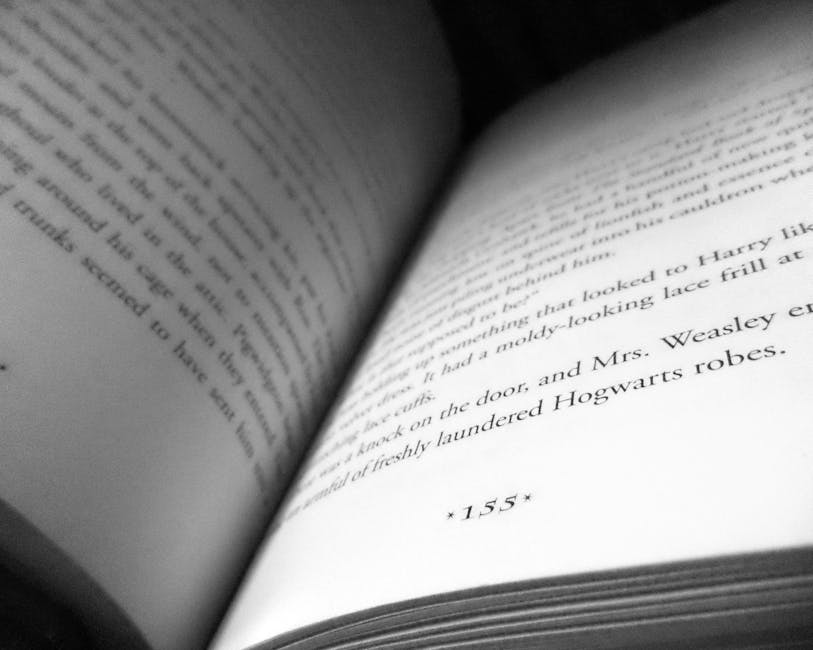Aku selalu berpikir bahwa kedewasaan adalah pencapaian, sebuah garis finis yang diraih setelah melewati serangkaian kesuksesan yang terencana. Sebagai seorang perancang muda, aku terobsesi pada kesempurnaan, memastikan setiap garis dan sudut dalam hidupku—sama seperti desainku—haruslah tanpa cela. Obsesi itulah yang membuatku merasa tak terkalahkan saat aku memenangkan tender proyek pembangunan kompleks seni terbesar.
Namun, hidup punya caranya sendiri untuk mengajarkan kerendahan hati. Kesalahan kecil dalam perhitungan material, yang awalnya kuanggap remeh, ternyata berakibat fatal; proyek itu ditarik kembali di tengah jalan. Malam itu, saat email pembatalan itu datang, duniaku runtuh, seolah fondasi yang kubangun dengan susah payah tiba-tiba ambruk menjadi debu.
Aku menghabiskan minggu-minggu berikutnya dalam kegelapan yang pekat, menolak panggilan dan membiarkan studio kecilku diselimuti kekacauan. Rasa malu dan pengkhianatan terhadap diri sendiri terasa lebih berat daripada beban batu yang gagal kupasang di proyek itu. Aku merasa gagal total, bukan hanya sebagai profesional, tetapi sebagai manusia yang telah berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu berhasil.
Dalam keputusasaan itu, aku mulai menenggelamkan diri dalam tumpukan sketsa lama, mencari di mana letak awal mula kesombonganku. Aku menyadari, selama ini aku hanya fokus pada hasil akhir yang indah, melupakan proses yang berlumur keringat dan risiko kegagalan yang selalu mengintai. Kesempurnaan yang kukejar ternyata adalah ilusi yang rapuh.
Suatu sore, saat membersihkan debu di gudang, tanganku menyentuh sebuah vas keramik tua milik mendiang kakekku, yang permukaannya dipenuhi retakan teknik kintsugi—seni memperbaiki keramik dengan emas. Keretakan itu tidak disembunyikan; justru dipertegas dan dihormati, menjadikannya lebih berharga. Vas itu seolah berbisik, bahwa keindahan sejati seringkali ditemukan dalam bekas luka yang telah diterima dan dirayakan.
Momen itu adalah titik balik yang menyakitkan namun mencerahkan. Aku mulai memahami bahwa kegagalan besar ini adalah babak krusial dalam Novel kehidupan yang sedang kutulis. Aku harus berhenti menuntut kesempurnaan yang steril dan mulai menerima kekacauan, karena kekacauan itulah yang membentuk karakter dan kedalaman.
Aku mengambil kembali pena desainku, bukan untuk menghapus kesalahan masa lalu, tetapi untuk merancang masa depan yang lebih jujur. Aku tidak lagi takut pada kritik atau kemungkinan jatuh lagi; aku justru merangkulnya sebagai bagian integral dari proses belajar. Kedewasaan ternyata bukan tentang tidak pernah jatuh, melainkan tentang kecepatan dan keberanian untuk bangkit setelah tersungkur.
Kegagalan itu memang merenggut impian besarku, tetapi ia memberiku sesuatu yang jauh lebih berharga: fondasi yang kuat, yang tidak lagi dibangun di atas ilusi, melainkan di atas pengalaman nyata. Retak yang dulu kuratapi kini menjadi peta yang jelas, menuntunku ke arah yang lebih otentik dan bermakna.
Aku kini tahu, menjadi dewasa adalah memahami bahwa setiap bekas luka adalah narasi, dan bahwa kisah yang paling menginspirasi adalah kisah tentang seseorang yang berani patah, lalu menemukan cara baru untuk bersinar. Namun, apakah aku benar-benar siap menghadapi tatapan para investor lama ketika aku kembali mengajukan proposal baru, membawa desain yang kini jauh lebih berani dan—ironisnya—jauh lebih manusiawi?