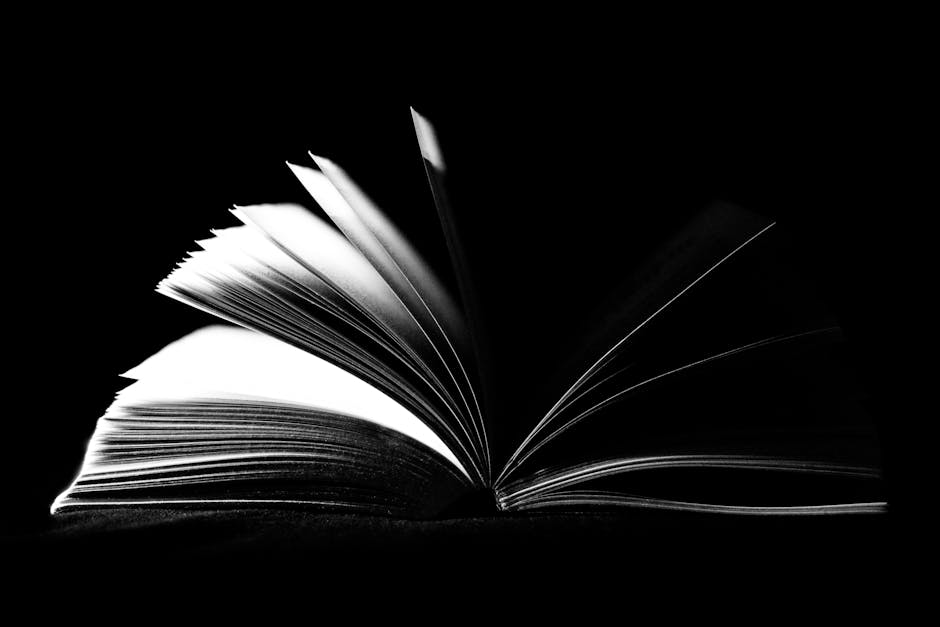Aroma serbuk kayu dan pernis selalu menjadi latar belakang kehidupanku, namun tak pernah kusangka ia akan menjadi panggung utamaku. Impianku sederhana: melarikan diri ke kota yang jauh, belajar seni murni, dan melukis kanvas yang tak terbatasi oleh dinding bengkel Ayah. Surat penerimaan dari akademi di luar negeri terlipat rapi di laci, menunggu waktu yang tepat untuk kubuka.
Waktu yang tepat itu tidak pernah datang. Sebaliknya, yang datang adalah kabar buruk tentang kesehatan Ayah, memaksa roda kehidupan berputar balik dengan kecepatan yang memusingkan. Bengkel Kayu Senja, warisan turun temurun keluarga, tiba-tiba berada di pundakku yang belum terbiasa memikul beban seberat itu.
Malam-malam pertama dihabiskan dengan mempelajari laporan keuangan yang rumit dan menghadapi tatapan skeptis para pengrajin senior. Aku, si bungsu yang biasanya hanya tahu cara memoles kayu, kini harus mengambil keputusan strategis tentang pembelian bahan baku dan negosiasi harga. Rasa takut itu seperti pasir yang merayap, menghambat setiap langkahku.
Puncak dari segala kepedihan adalah saat aku menarik surat penerimaan itu keluar dari laci dan merobeknya perlahan. Itu bukan hanya selembar kertas; itu adalah peta menuju masa depan yang telah kubayangkan sejak remaja, kini hancur menjadi serpihan kecil di lantai. Aku memilih warisan, memilih tanggung jawab, di atas kebebasan yang selama ini kudamba.
Awalnya aku memimpin dengan rasa gentar, mencoba meniru gaya Ayah yang tegas dan berwibawa. Namun, kegagalan demi kegagalan kecil mengajariku bahwa kepemimpinan sejati bukanlah imitasi, melainkan otentisitas yang dibalut keberanian. Aku mulai mendengarkan para pengrajin, menggabungkan ide seni modernku dengan teknik ukiran tradisional mereka.
Perlahan, Kayu Senja mulai menemukan ritme baru. Aku belajar bahwa mengelola manusia jauh lebih sulit daripada mengelola keuangan, tetapi juga jauh lebih memuaskan. Melihat produk baru kami dipajang dan mendapat apresiasi, ada kebanggaan yang berbeda—bukan kebanggaan seorang seniman, melainkan kebanggaan seorang nahkoda.
Setiap pagi, saat kayu-kayu itu diukir, aku menyadari bahwa aku sedang mengukir diriku sendiri, membentuk sudut-sudut yang tajam dan menghaluskan permukaan yang kasar. Ini adalah babak paling nyata dalam Novel kehidupan yang harus kujalani, penuh dengan revisi dan plot twist tak terduga. Aku mulai memahami, kedewasaan bukanlah usia, melainkan seberapa cepat kita mampu bangkit setelah mimpi kita dipatahkan.
Aku belajar dari Ayah, yang kini hanya bisa mengawasi dari kursi rodanya, bahwa cinta terbesar bukanlah pada apa yang kita dapatkan, melainkan pada apa yang rela kita korbankan. Pengorbanan itu, yang dulu terasa seperti belenggu, kini menjelma menjadi sayap yang memberiku kekuatan untuk terbang lebih tinggi dari yang kubayangkan.
Mungkin aku tidak akan pernah melukis di galeri impianku, tetapi aku telah menciptakan mahakarya yang lebih besar: sebuah keluarga yang utuh dan sebuah warisan yang bertahan. Sekarang, aku menatap langit-langit bengkel, bertanya-tanya tantangan apa lagi yang akan dilemparkan oleh takdir, dan aku tersenyum. Sebab, aku tahu, kali ini aku sudah siap.