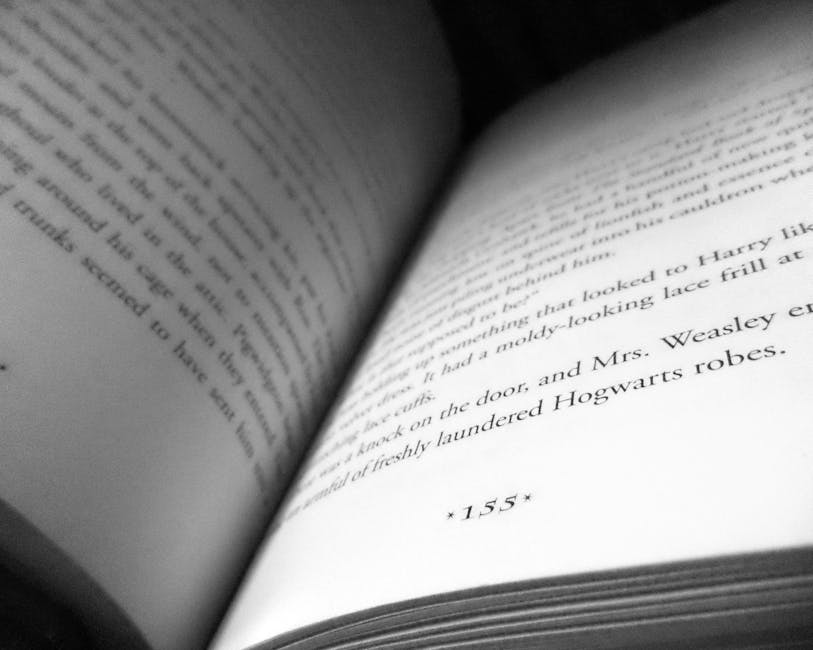Aku selalu berpikir bahwa kedewasaan adalah garis finis yang akan kucapai saat usiaku menyentuh angka tertentu, sebuah hadiah yang datang otomatis bersama waktu. Kehidupanku kala itu terasa seperti sungai yang tenang; mengalir tanpa hambatan besar, penuh rencana indah yang disusun rapi di atas kertas-kertas impian. Aku adalah si bungsu yang terlindungi, yang hanya tahu cara bermimpi tinggi tanpa pernah menyentuh tanah.
Namun, sungai itu tiba-tiba membeku. Kabar penutupan mendadak usaha kecil keluarga kami, yang menjadi satu-satunya sandaran, datang seperti pukulan telak yang merenggut semua kepastian. Malam itu, aku melihat ayah dan ibu, dua pilar kekuatanku, terlihat begitu rapuh di bawah sorot lampu ruang tengah.
Rencana kuliahku di luar kota, yang sudah kususun sejak lama, harus kumasukkan kembali ke dalam laci. Prioritas berubah drastis dari mengejar beasiswa menjadi mencari pekerjaan apa pun yang bisa menopang biaya harian dan membayar tumpukan tagihan yang tak terduga. Rasanya seperti dipaksa mengenakan sepatu bot yang terlalu besar dan disuruh berlari di medan yang asing.
Aku memulai dengan pekerjaan serabutan, menghadapi penolakan demi penolakan, dan belajar keras bahwa dunia nyata tidak peduli seberapa cerdas nilaiku di sekolah. Ada hari-hari ketika aku pulang dengan kaki pegal dan hati remuk, bertanya-tanya mengapa takdir begitu kejam merenggut masa mudaku.
Puncaknya adalah saat aku harus menjual beberapa barang kesayanganku, termasuk kamera tua yang selalu kubawa untuk merekam momen. Bukan karena nilai uangnya, melainkan karena perpisahan dengan benda itu terasa seperti mengubur sebagian dari diriku yang lama—diriku yang bebas dari beban.
Saat itulah aku menyadari bahwa dewasa bukanlah tentang tidak pernah menangis, melainkan tentang kemampuan untuk menghapus air mata itu sendiri dan tetap melangkah maju. Kedewasaan adalah pilihan sadar untuk memikul beban, bahkan saat pundak terasa terlalu kecil untuk menampungnya.
Perjalanan ini, dengan segala pahit getirnya, adalah babak paling krusial dalam Novel kehidupan yang sedang kutulis. Setiap kegagalan, setiap malam tanpa tidur karena menghitung uang receh, dan setiap senyuman yang kuberikan pada orang tuaku meskipun hatiku lelah, menjadi tinta yang membentuk karakternya.
Aku tidak lagi Risa yang hanya tahu cara bermimpi; kini aku Risa yang tahu cara membangun dari puing-puing. Tatapan mata orang tuaku yang kini penuh kebanggaan, bukan lagi rasa kasihan, adalah hadiah terindah yang tak ternilai harganya. Mereka melihat bukan hanya anak, tetapi seorang rekan seperjuangan.
Lalu, di tengah kekacauan itu, sebuah tawaran tak terduga datang dari mentor lama ayah, sebuah kesempatan untuk kembali merintis usaha kecil dengan modal yang sangat terbatas. Aku tahu, ini akan menjadi pertarungan yang jauh lebih berat dari sebelumnya, tetapi kini aku tidak takut. Sebab, aku telah belajar bahwa badai bukan untuk dihindari, melainkan untuk dilewati, dan di ujung sana, kedewasaan menanti sebagai mahkota yang terbuat dari ketangguhan.