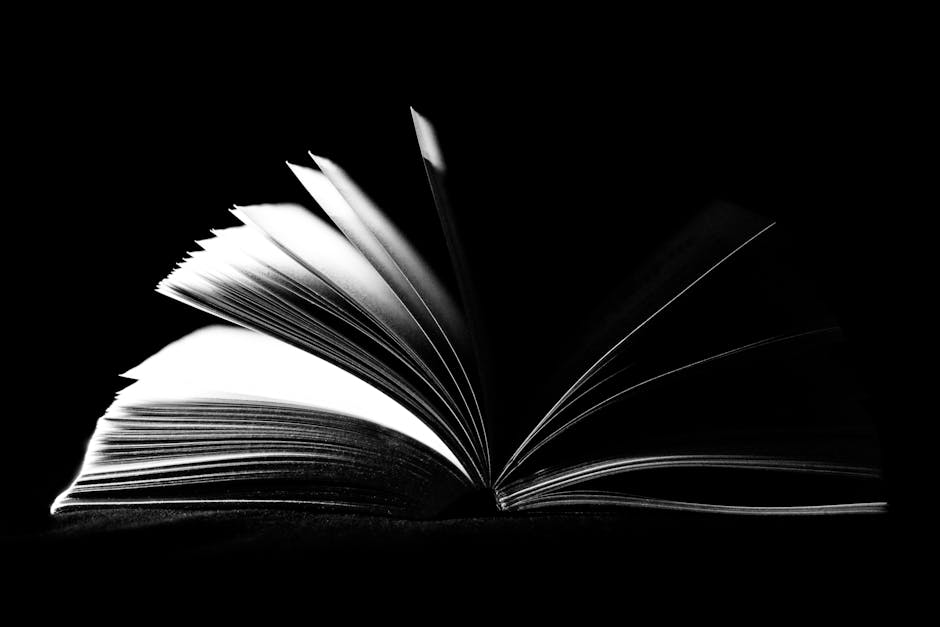Aku selalu hidup dalam zona nyaman yang dihiasi kemudahan. Dinding-dinding hidupku dibangun dari janji-janji masa depan cerah yang sudah diatur, tanpa pernah sedikit pun membayangkan batu sandungan yang nyata. Aku adalah versi diriku yang naif, yang mengira badai hanyalah cerita fiksi dalam buku.
Kehancuran itu datang bukan dalam bentuk gempa besar, melainkan melalui surat elektronik yang dingin dan formal. Sebuah kelalaian kecil dalam administrasi membuat beasiswaku—satu-satunya jaminan masa depanku—dicabut tanpa kompromi. Dalam sekejap, karpet mewah yang kupijak ditarik, meninggalkanku terjerembap di lantai realitas yang keras.
Malam-malam pertama dihabiskan dalam tangisan dan pertanyaan tak berujung tentang keadilan semesta. Namun, tangis tak pernah membayar biaya kuliah semester depan atau mengisi perut yang lapar. Aku sadar, masa berkabung harus segera berakhir, karena jika aku tidak bergerak, aku akan tenggelam sepenuhnya.
Keputusan itu terasa berat, namun harus dilakukan: berhenti mengeluh dan mulai bekerja. Aku mengambil dua pekerjaan paruh waktu—menjadi pelayan kafe di pagi hari dan tutor privat di malam hari—hanya demi mengumpulkan sisa-sisa harapan untuk tetap melanjutkan studi. Lelah fisik dan mental adalah teman setia yang kini menemaniku setiap hari, menggantikan buku-buku tebal yang dulu kubaca dengan santai.
Di kafe, aku belajar arti senyum palsu yang harus tetap dipertahankan meski hati sedang remuk. Aku melihat bagaimana orang-orang berjuang hanya untuk mendapatkan tip receh, dan tiba-tiba, uang seribu rupiah terasa jauh lebih berharga daripada semua uang saku yang dulu kuhamburkan tanpa pikir panjang.
Saat itulah aku menyadari bahwa kehidupan ini adalah sebuah panggung besar yang tak terduga, sebuah Novel kehidupan yang babak-babaknya ditulis oleh pilihan dan konsekuensi, bukan oleh impian manis semata. Kedewasaan bukanlah tentang usia, melainkan tentang seberapa cepat kita bangkit setelah dihempaskan.
Ada momen ketika aku hampir menyerah, berdiri di depan ATM dengan saldo yang sangat minim, sementara tenggat pembayaran sudah di depan mata. Namun, aku terus maju, sedikit demi sedikit, berkat dukungan tak terduga dari kenalan baru yang juga sedang berjuang. Kami menjadi sandaran satu sama lain dalam badai.
Akhirnya, aku berhasil membayar cicilan kuliah pertamaku dari hasil keringat sendiri. Air mata yang tumpah kali ini berbeda; ini adalah air mata kemenangan, bukan keputusasaan. Aku melihat bayanganku di cermin, dan sosok yang berdiri di sana bukanlah Risa yang manja dari masa lalu, melainkan seseorang yang matanya dipenuhi ketegasan dan bekas luka perjuangan.
Pengalaman pahit itu telah menjadi guru terbaik, merenggut semua keangkuhanku dan menggantinya dengan empati serta ketangguhan baja. Sekarang, aku tidak takut lagi pada kegagalan, sebab aku tahu, setiap kali aku jatuh, aku akan selalu menemukan cara untuk berdiri. Namun, apakah kekuatan baru ini cukup untuk menghadapi rahasia besar keluarga yang mulai terkuak di tengah perjuanganku?