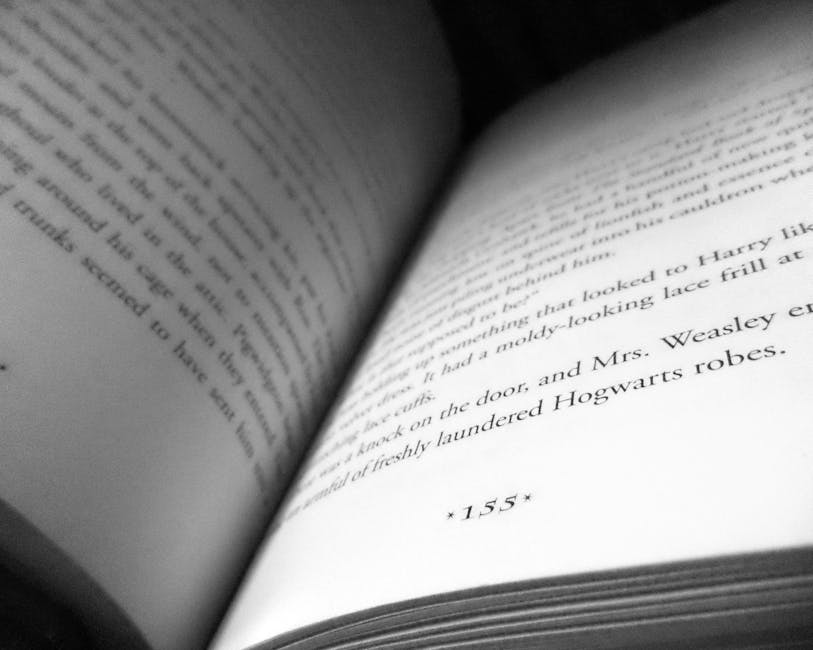Aku selalu percaya bahwa semangat muda adalah modal utama untuk mengubah dunia. Dengan idealisme yang membara dan rencana yang disusun rapi, aku memulai proyek besar: mendirikan rumah baca komunitas di sudut kota yang paling terabaikan. Aku yakin, hanya perlu kemauan keras dan sedikit keberuntungan untuk melihat benih perubahan itu tumbuh.
Semua berjalan indah pada awalnya; donasi mengalir, relawan bersemangat, dan tawa anak-anak mulai mengisi ruangan. Aku mabuk oleh rasa percaya diri, mengira bahwa kesulitan hanyalah detail kecil yang bisa disingkirkan dengan senyuman. Aku lupa bahwa kehidupan tidak pernah semudah halaman pertama sebuah buku cerita.
Pukulan itu datang tak terduga, secepat petir menyambar di musim kemarau. Sponsor utama menarik diri, dan dana operasional kami ludes karena kesalahan perhitungan yang kusepelekan. Dalam semalam, impian yang kubangun dengan keringat dan air mata itu runtuh, menyisakan puing-puing rasa malu dan kekecewaan yang menusuk.
Aku mengunci diri selama berminggu-minggu, membiarkan kegagalan itu merobek setiap helai keyakinanku. Cermin di kamar hanya menampilkan sosok asing yang rapuh, jauh dari citra aktivis muda yang selalu kukoar-koarkan. Aku merasa telah mengecewakan semua orang, terutama diriku yang naif.
Di tengah keputusasaan itu, Ibu datang membawa secangkir teh hangat dan sebuah kalimat sederhana: “Jatuh bukanlah akhir, Nak. Itu hanya jeda untuk mengatur napas.” Ibu tidak mencoba memperbaiki puing-puing itu; ia hanya menemaniku melihat reruntuhan dengan mata yang lebih tenang.
Momen itulah yang menjadi titik balik, saat aku sadar bahwa kedewasaan bukanlah tentang menghindari kegagalan, melainkan tentang menerima bekas lukanya. Aku mulai membaca ulang Novel kehidupan yang selama ini kujalani, menyadari bahwa setiap bab buruk adalah fondasi untuk babak selanjutnya yang lebih kuat. Aku belajar bahwa bantuan sejati datang dari kolaborasi tulus, bukan dari idealisme heroik yang sendirian.
Aku kembali ke komunitas, bukan untuk membangun rumah baca yang sama, melainkan untuk membantu membersihkan puingnya, bahu-membahu dengan para relawan yang masih tersisa. Kami tidak lagi mencari sorotan besar, tetapi fokus pada aksi kecil yang berkelanjutan, seperti berbagi buku dari pintu ke pintu.
Kegagalan itu mengikis kesombonganku dan menggantinya dengan empati yang mendalam. Aku tidak lagi melihat orang sebagai penonton yang harus diyakinkan, tetapi sebagai rekan seperjalanan yang sama-sama berjuang. Kedewasaan ternyata adalah seni menerima ketidaksempurnaan, baik pada diri sendiri maupun pada dunia.
Kini, meski rumah baca itu belum berdiri lagi, aku membawa pelajaran berharga: bahwa luka yang kita sembunyikan adalah peta menuju kekuatan yang belum kita sadari. Pertanyaannya, setelah badai ini mereda, babak seperti apa yang akan kutulis selanjutnya?