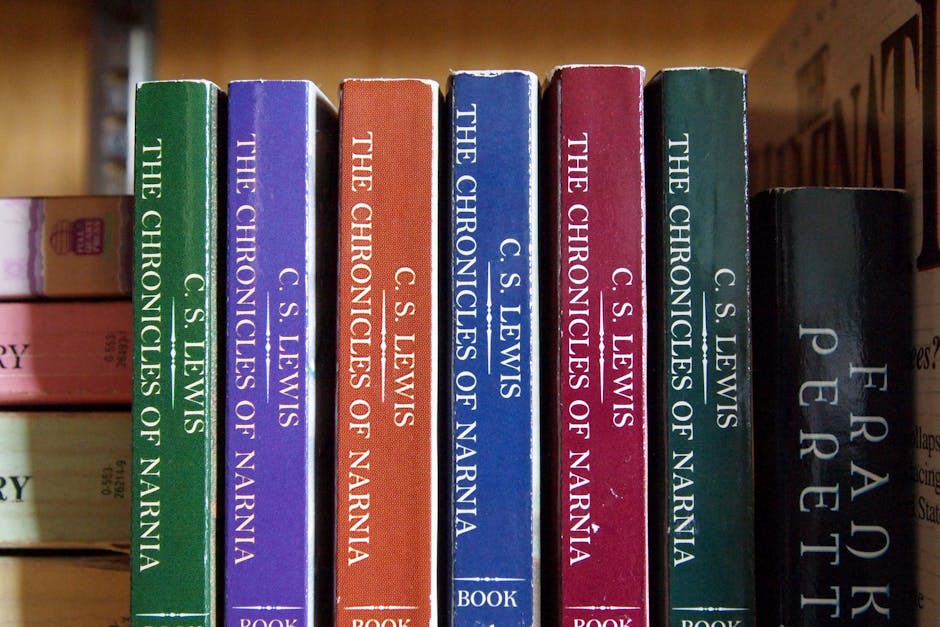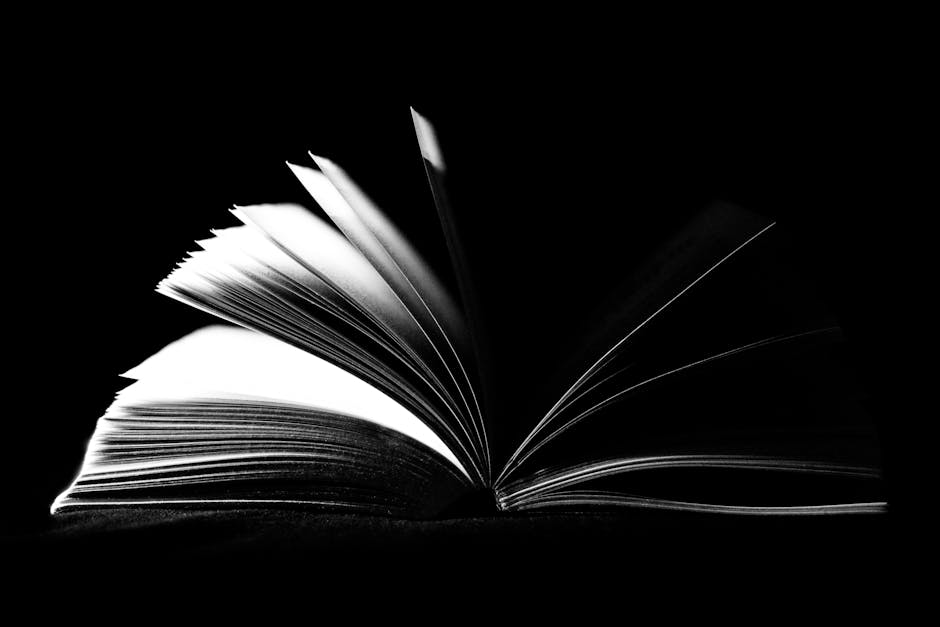Dulu, dunia bagiku hanyalah kanvas luas yang menunggu untuk diwarnai dengan ambisi pribadi dan janji-janji masa depan yang gemerlap. Aku selalu berpikir kedewasaan adalah pencapaian usia, bukan akumulasi luka yang perlahan menguatkan tulang punggung. Aku adalah gadis yang hanya tahu cara bermimpi, bukan cara bertahan.
Segalanya berubah ketika Ayah tiba-tiba harus beristirahat total. Bengkel tua yang selama ini menjadi nafas keluarga, kini terancam gulung tikar. Aku, yang selama ini sibuk merencanakan kuliah di luar kota, mendapati diriku duduk di kursi kasir yang berdebu, mencoba memahami tumpukan kuitansi dan daftar hutang yang menjulang tinggi.
Kejutan terbesarnya bukanlah kesulitan teknis memperbaiki mesin, melainkan menghadapi wajah-wajah manusia yang menuntut dan terkadang mengkhianati kepercayaan. Aku belajar bahwa senyum ramah seorang pelanggan bisa menyembunyikan niat buruk, dan bahwa janji lisan sering kali lebih rapuh daripada kertas tipis.
Mimpi-mimpi besarku harus kuletakkan di laci paling belakang. Uang yang seharusnya menjadi biaya pendaftaran kuliah, kini menguap untuk membayar tunggakan suku cadang dan gaji para montir. Ada rasa pahit yang menusuk, sebuah pengorbanan yang terasa sangat tidak adil bagi jiwa muda yang haus akan kebebasan.
Malam-malam panjang di bengkel, ditemani aroma oli dan besi, menjadi sekolah pribadiku. Aku tidak hanya belajar tentang manajemen inventaris, tetapi juga tentang manajemen emosi. Aku harus menelan rasa malu saat menawar harga atau menagih pembayaran, sebuah seni ketegasan yang tak pernah diajarkan di buku pelajaran manapun.
Saat itulah aku menyadari bahwa apa yang kualami ini adalah skenario paling jujur dan brutal dari sebuah alur cerita. Ini adalah Novel kehidupan, di mana penulisnya tak pernah memberiku sinopsis, hanya tantangan yang harus kuhadapi bab demi bab tanpa persiapan.
Perlahan, aku menemukan kekuatan yang tak kusangka ada di dalam diriku. Kekuatan untuk berdiri tegak di tengah badai, kekuatan untuk mengatakan ‘tidak’ tanpa merasa bersalah, dan yang paling penting, kekuatan untuk memaafkan diri sendiri ketika melakukan kesalahan. Bengkel tua itu tidak hanya memberiku beban, tetapi juga memberiku fondasi yang kokuh.
Aku mulai melihat Ayah dengan mata yang berbeda; bukan lagi sebagai sosok yang menyediakan, melainkan sebagai pejuang yang menanggung beban ini sendirian selama bertahun-tahun. Rasa syukur kini menggantikan rasa sesal atas waktu mudaku yang terenggut.
Kedewasaan datang bukan saat kita berhasil meraih semua yang kita inginkan, tetapi saat kita menerima dengan lapang dada apa yang harus kita korbankan. Aku berhasil menyelamatkan bengkel itu, namun harga yang kubayar adalah hilangnya kepolosan. Kini, aku berdiri di ambang pintu, siap menghadapi dunia, bertanya-tanya: setelah melewati badai ini, apakah aku akan mampu meraih kembali mimpi lamaku, atau apakah takdir telah menyiapkan kanvas yang sama sekali baru?