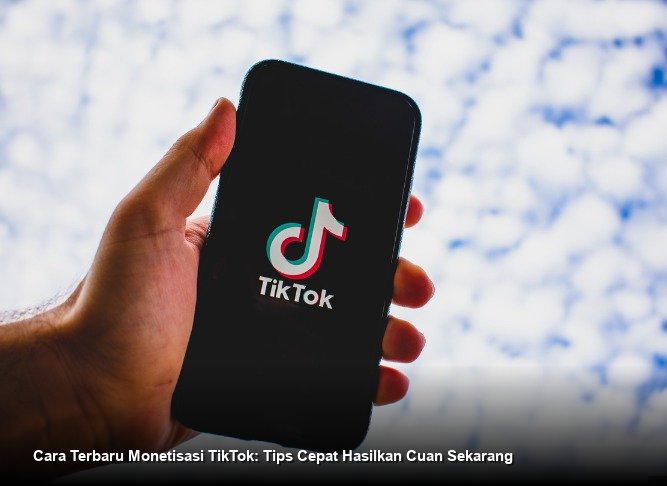Hidupku sebelum badai hanyalah rangkaian hari-hari yang nyaman, seperti sungai yang mengalir tenang tanpa pernah bertemu jeram. Aku adalah Risa yang manja, yang percaya bahwa jaring pengaman keluarga akan selalu ada, siap menangkapku kapan pun aku terjatuh. Namun, ketika pilar utama itu runtuh tanpa peringatan, aku terlempar ke tengah hutan belantara yang gelap, sendirian dan tanpa kompas.
Guncangan itu datang dalam wujud tanggung jawab yang tiba-tiba melilit leherku, memaksa mataku terbuka melihat realitas yang keras. Aku harus belajar membaca laporan keuangan yang rumit, menghadapi tatapan skeptis para relasi bisnis ayah, dan yang terberat, menenangkan hati ibuku yang hancur. Rasa takut itu menusuk, dingin dan tajam, membuatku seringkali menangis di balik selimut sebelum fajar menyingsing.
Ada saatnya aku ingin menyerah saja, kembali menjadi Risa yang lama, yang hanya peduli pada warna lipstik dan rencana liburan. Beban itu terlalu berat untuk pundak yang selama ini hanya terbiasa membawa tas tangan. Aku merasa seolah aku sedang memainkan peran yang bukan milikku, berakting menjadi dewasa sementara di dalam hati, aku masih gadis kecil yang ketakutan.
Kegagalan pertama datang dengan pahit, sebuah proyek yang aku tangani hancur berantakan karena kesalahan perhitungan yang bodoh. Saat itu, aku duduk di lantai kantor yang dingin, menyadari bahwa kepintaran saja tidak cukup; yang dibutuhkan adalah ketahanan mental yang ditempa oleh api. Rasa malu itu membakar egoku, tetapi anehnya, ia juga menyalakan sesuatu yang baru di dalam diriku: tekad.
Perlahan, aku mulai menerima bahwa rasa sakit ini adalah guru terbaik yang pernah kumiliki. Setiap air mata dan setiap malam tanpa tidur adalah babak baru yang membentuk karakterku. Aku mulai memahami bahwa kedewasaan sejati bukanlah tentang usia yang tertera di KTP, melainkan kemampuan untuk berdiri tegak setelah badai merenggut segalanya.
Aku menyadari bahwa semua pengalaman ini, baik yang menyakitkan maupun yang membanggakan, adalah lembaran-lembaran penting dalam Novel kehidupan yang sedang kutulis. Aku bukan lagi korban keadaan; aku adalah penulis yang memegang pena takdirku sendiri. Membaca kembali bab-bab yang penuh luka, aku menemukan peta menuju kekuatanku yang tersembunyi.
Kini, ketika aku melihat pantulan diriku di cermin, aku melihat sorot mata yang berbeda. Bukan lagi sorot mata yang penuh kecemasan, melainkan sorot mata seorang pejuang yang telah melewati medan perang. Aku belajar bahwa kehilangan tidak selalu berarti akhir; terkadang, itu adalah ruang kosong yang diciptakan alam semesta agar kita bisa mengisi dengan versi diri yang lebih kuat.
Aku masih belum mencapai garis akhir, tentu saja. Perjalanan ini panjang dan penuh liku, namun kini aku melangkah dengan keyakinan yang dulu tak pernah kumiliki. Aku telah menemukan kedamaian dalam ketidakpastian, dan aku tahu, aku tidak akan pernah kembali menjadi Risa yang hanya menunggu diselamatkan.
Lalu, pertanyaan muncul: Jika aku bisa kembali ke masa lalu, apakah aku akan mencegah badai itu datang? Mungkin tidak. Sebab, tanpa kehancuran itu, aku tidak akan pernah tahu seberapa kokoh fondasi yang ternyata tersembunyi di dalam diriku. Dan kini, babak baru telah dimulai, babak di mana aku harus membuat keputusan yang akan mengubah nasib bukan hanya diriku, tapi juga warisan yang harus kupertahankan. Akankah aku berhasil?