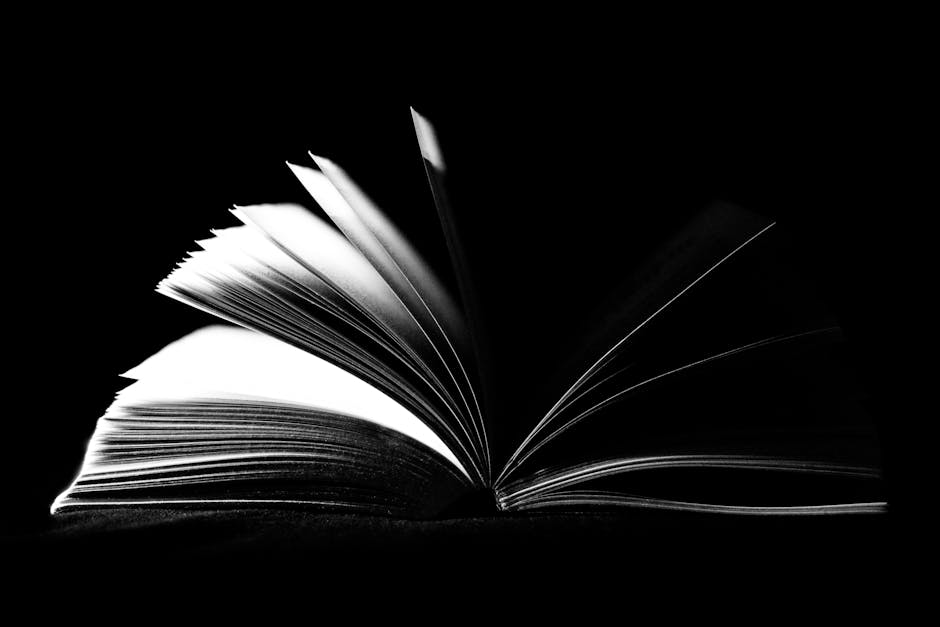Aku selalu percaya bahwa hidup harus rapi, terstruktur, seperti garis-garis presisi yang kubuat di atas kertas arsitekturku. Obsesiku terhadap kesempurnaan membuatku kebal terhadap kesalahan, atau setidaknya, aku berusaha keras agar tak ada cela sedikit pun yang menodai catatan prestasiku. Aku hidup dalam kotak kaca yang kubangun sendiri, aman dari debu dan kekecewaan.
Namun, kotak kaca itu pecah berkeping-keping saat proyek terbesar dalam karirku—yang sudah kurencanakan selama berbulan-bulan—hancur karena kesalahan teknis kecil yang luput dari pengawasanku. Kegagalan itu terasa seperti pukulan telak yang merobek seluruh identitasku; aku bukan lagi Risa yang sempurna, aku hanyalah tumpukan puing-puing rasa malu. Aku mengurung diri, menolak cahaya, dan membiarkan keputusasaan menjadi selimut tebal yang memelukku erat.
Selama berminggu-minggu, aku hanya menatap langit-langit, mencoba memahami di mana letak kesalahan terbesarku. Aku mencari kambing hitam, menyalahkan keadaan, dan yang paling parah, menyalahkan diriku sendiri atas segala hal yang berada di luar kendaliku. Aku merasa duniaku telah berakhir, padahal kenyataannya, duniaku baru saja akan dimulai.
Titik balik itu datang saat aku bertemu seorang pemahat kayu tua di tepi kota, Pak Bima, yang tangannya dipenuhi bekas sayatan dan kapalan. Ia melihat sketsa yang kucoret-coret penuh amarah di buku catatan, sketsa yang sengaja kurobek-robek karena tak mencapai standar ideal. Pak Bima tersenyum, senyum yang terasa hangat dan penuh pengertian.
Ia mengatakan bahwa kayu yang paling indah adalah kayu yang pernah mengalami badai, yang memiliki urat dan bekas luka yang unik. Ia berbisik pelan bahwa hidup ini adalah sebuah proses yang kacau, tidak ada yang sempurna, dan itulah keindahannya yang sesungguhnya. Aku sadar, kisah perjalanan ini adalah bagian penting dari sebuah Novel kehidupan yang harus kubaca sampai tuntas, bukan sekadar melompati bab-bab yang menyakitkan.
Perlahan, aku mulai merangkai kembali pecahan diriku, bukan untuk kembali menjadi sempurna, melainkan untuk menjadi utuh. Aku mulai menerima bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan titik koma yang memungkinkan kalimat baru dimulai. Aku belajar bahwa kedewasaan sejati bukan tentang menghindari jatuh, tetapi tentang keberanian untuk bangkit, meskipun lutut masih berdarah.
Aku kembali bekerja, namun kali ini dengan perspektif yang berbeda. Garis-garis yang kubuat kini lebih luwes, tidak kaku, dan aku membiarkan sedikit ketidaksempurnaan menghiasi karyaku sebagai pengingat akan proses yang telah kulalui. Setiap bekas luka di hati dan di sketsaku kini menjadi narasi yang menguatkan, bukan lagi aib yang harus kusembunyikan.
Kedewasaan ternyata adalah seni menerima bahwa kita tidak pernah benar-benar memegang kendali, dan bahwa cahaya paling terang sering kali datang dari celah retakan yang kita kira adalah kehancuran. Kini, aku berdiri di tepi senja, siap menyambut babak baru, bertanya-tanya, kejutan apa lagi yang disiapkan takdir di halaman berikutnya?