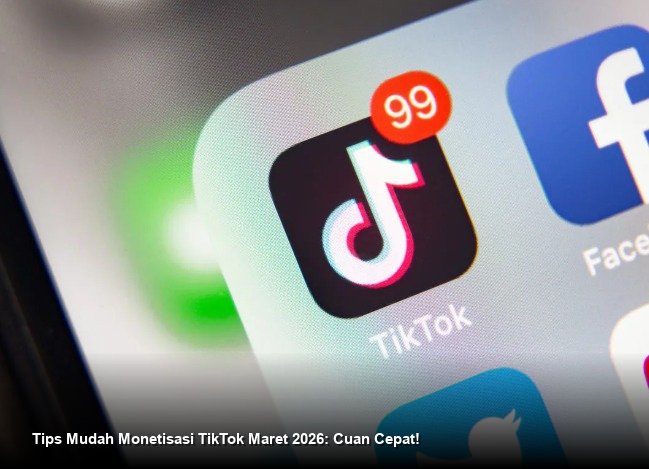Risa selalu percaya bahwa hidup adalah sebuah struktur yang harus direncanakan dengan presisi mutlak, layaknya sketsa arsitektur yang ia genggam erat. Ia telah menginvestasikan seluruh jiwanya pada proyek menara kota yang megah, sebuah monumen yang ia yakini akan menjadi bukti kehebatan dan kesempurnaan dirinya. Ambisi itu adalah api yang membakar, sekaligus dinding yang mengisolasi.
Namun, semesta memiliki rencana yang jauh lebih kacau dari garis lurus pada kertas kalkir. Tiba-tiba, proyek itu dibatalkan—bukan karena kegagalan desain, melainkan karena perubahan politik yang tak terduga. Dalam sekejap, fondasi yang ia bangun selama bertahun-tahun runtuh, meninggalkan debu pahit di lidahnya dan lubang menganga di dadanya.
Ia menghabiskan berminggu-minggu dalam keheningan yang dingin, menatap langit-langit seolah mencari jawaban dari Tuhan tentang keadilan. Harga dirinya hancur berkeping-keping, dan ia mulai meragukan apakah ketekunan yang ia banggakan selama ini hanyalah bentuk keras kepala yang buta. Kedewasaan terasa seperti janji palsu yang jauh.
Titik balik itu datang secara tidak sengaja, melalui permintaan seorang profesor lama untuk membimbing mahasiswa tingkat akhir yang kesulitan. Namanya Dika, pemuda yang terlalu takut membuat kesalahan hingga ia lumpuh dalam proses kreatifnya. Risa melihat bayangan dirinya yang lebih muda dalam ketakutan Dika.
Awalnya, Risa mengajar dengan keangkuhan seorang mentor yang terluka, namun perlahan, proses itu memaksanya untuk membongkar kembali prinsip-prinsipnya sendiri. Ia harus menjelaskan kepada Dika bahwa sketsa yang salah, yang dirobek dan digambar ulang, justru adalah bagian paling berharga dari sebuah mahakarya. Inilah babak paling esensial dalam Novel kehidupan yang harus ia jalani.
Mengamati Dika berjuang dan akhirnya menemukan kepercayaan dirinya, Risa menyadari bahwa ia terlalu fokus pada hasil akhir, melupakan keindahan dari proses yang berantakan. Kedewasaan bukanlah tentang membangun menara yang sempurna, melainkan tentang memiliki kekuatan untuk bertahan di tengah gempa, bahkan ketika menara itu jatuh.
Ia mulai menerima bahwa kegagalan bukanlah lawan dari kesuksesan, melainkan bahan baku yang membentuk karakter. Ia belajar melepaskan kendali atas apa yang tidak bisa ia ubah, dan fokus pada bagaimana ia akan merespons kehancuran tersebut. Jiwanya yang semula kaku kini mulai lentur, mampu menampung rasa sakit tanpa harus patah.
Risa kini duduk di mejanya, bukan lagi dengan ketakutan akan sketsa yang salah, melainkan dengan penerimaan yang lapang. Ia tahu menara kota itu mungkin tidak akan pernah berdiri, tetapi ia telah membangun sesuatu yang jauh lebih kokoh di dalam dirinya. Ia tersenyedia, siap memulai desain baru, desain yang tidak hanya ambisius, tetapi juga manusiawi.