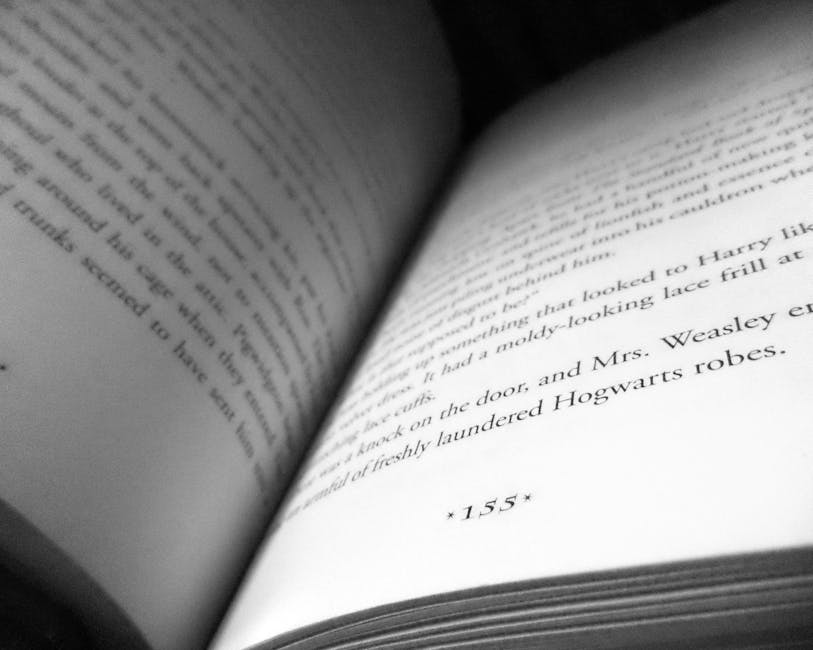Aku selalu membayangkan hidupku akan dimulai dengan aroma cat minyak dan kebebasan di kota yang jauh. Rencana sudah tertata rapi: beasiswa seni, tiket pesawat ke benua Eropa, dan janji untuk tidak pernah kembali ke kota kecil ini kecuali saat liburan. Di mataku, rumah dan usaha batik warisan keluarga hanyalah jangkar yang menahan laju ambisiku.
Namun, takdir memiliki skenario yang jauh lebih dramatis dan menyakitkan. Tepat di malam sebelum keberangkatan, kakek jatuh sakit parah, dan bersamaan dengan itu, kabar buruk datang: pembatalan pesanan besar yang membuat usaha batik kami terancam gulung tikar. Seketika, impian yang kubangun bertahun-tahun runtuh menjadi serpihan debu di lantai.
Aku menatap koper yang sudah terisi penuh, lalu beralih pada wajah ayah dan ibu yang terlihat menua sepuluh tahun dalam semalam. Dalam keheningan yang mencekam itu, aku tahu aku harus membuat keputusan yang mengubah segalanya. Tiket pesawat itu kubatalkan, dan buku-buku sketsa kutumpuk di sudut, digantikan tumpukan laporan keuangan yang rumit.
Bulan-bulan pertama adalah neraka yang dingin. Aku yang hanya tahu cara memadukan warna, kini harus berhadapan dengan utang, negosiasi yang keras, dan tatapan skeptis para karyawan senior. Setiap hari adalah pertarungan untuk membuktikan bahwa aku, gadis yang baru saja lulus sekolah, mampu memanggul beban yang begitu berat di pundak.
Aku belajar tentang pengorbanan, bukan lagi sebagai konsep puitis, melainkan sebagai tindakan nyata yang terasa menusuk dada. Aku harus menjual beberapa aset pribadi yang sangat berharga demi membayar gaji para pekerja, memastikan dapur mereka tetap mengepul meskipun dapur kami sendiri terasa hampa.
Dalam kelelahan yang luar biasa, aku mulai menyadari bahwa setiap kesulitan ini adalah babak penting yang tak terhindarkan. Ini adalah bagian wajib dari sebuah buku yang harus kita tulis sendiri, sebuah skrip pahit manis yang disebut Novel kehidupan. Kedewasaan bukanlah tentang usia, melainkan tentang seberapa banyak badai yang telah kita lalui tanpa kehilangan kemanusiaan kita.
Perlahan, usaha itu bangkit. Aku tidak lagi menganggap kain batik sebagai warisan yang membelenggu, melainkan sebagai kanvas tempat aku menumpahkan seluruh daya juang dan kreativitas yang sesungguhnya. Aku mulai mendesain ulang motif, menyuntikkan semangat baru, dan menemukan bahwa seni sejati ada pada proses bertahan hidup.
Ketika akhirnya aku berdiri tegak di depan para pekerja, memberikan arahan dengan suara yang mantap, aku tahu Risa yang dulu sudah mati. Ia digantikan oleh seseorang yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan yang paling penting, seseorang yang tidak lagi takut pada kenyataan. Kini, impianku bukan hanya tentang melukis di Paris, tetapi tentang memastikan bahwa akar yang telah memberiku kehidupan ini tidak pernah tercabut.