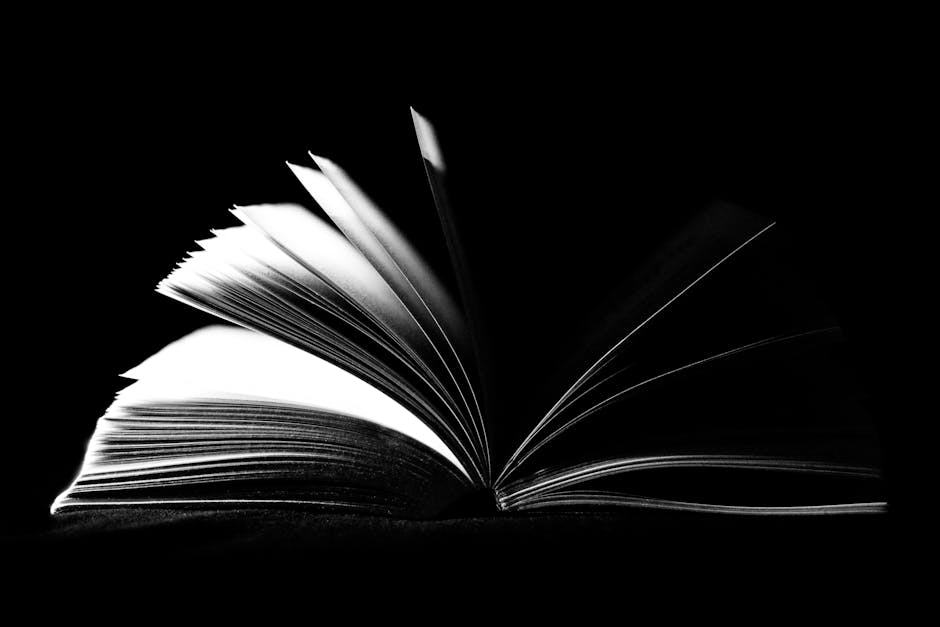Dunia Risa selama ini hanya berputar pada aroma cat minyak, kanvas, dan pujian dari para kritikus seni. Ia hidup dalam gelembung idealisme, percaya bahwa keindahan adalah satu-satunya mata uang yang berarti, tanpa pernah peduli pada angka-angka kaku atau hiruk pikuk urusan bisnis yang selalu diurus ayahnya. Kehidupan terasa lembut, seperti kuas yang meluncur di atas linen halus.
Semua berubah pada satu sore yang dingin, ketika telepon dari rumah sakit memecah ketenangan studio. Ayah Risa kolaps, dan bersamaan dengan itu, Risa menemukan tumpukan surat peringatan bank yang tersembunyi di laci meja kerja. Galeri seni yang menjadi rumah dan naungan mereka ternyata berada di ambang kehancuran finansial.
Tiba-tiba, palet warna Risa berubah total; merah bukan lagi gairah, melainkan alarm bahaya, dan hitam adalah ketidakpastian yang mencekik. Ia harus mengganti kuas dengan kalkulator, menghadapi para kreditor yang dingin, dan belajar memahami bahasa kontrak yang rumit. Risa yang biasanya hanya berinteraksi dengan sesama seniman kini dipaksa duduk di meja negosiasi, mencari jalan keluar dari labirin utang yang tak pernah ia ciptakan.
Ada malam-malam di mana ia hanya bisa menangis di tengah galeri yang sepi, bertanya mengapa takdir sekejam ini memaksanya meninggalkan impian demi tanggung jawab yang terasa terlalu berat. Ia merindukan masa-masa ketika masalah terbesarnya hanyalah mencari gradasi biru yang sempurna untuk langit senja. Tekanan itu seperti beban balok marmer yang diletakkan di atas dadanya.
Namun, di tengah keputusasaan itu, Risa menemukan kekuatan yang tak ia duga. Ia menyadari bahwa idealisme tanpa realisme hanyalah ilusi yang rapuh. Ia mulai membaca, belajar, dan melawan—bukan dengan emosi, tetapi dengan strategi dan perhitungan yang matang.
Setiap penolakan, setiap kegagalan kecil dalam negosiasi, bukan lagi pukulan yang mematikan, melainkan pelajaran berharga yang mengasah ketajamannya. Risa mulai berani mengambil keputusan sulit, menjual beberapa koleksi pribadi ayahnya demi menambal lubang terbesar, dan memberhentikan staf yang tidak efisien.
Inilah babak paling jujur dalam Novel kehidupan yang ia jalani, di mana keindahan sejati bukan terletak pada hasil akhir karya seni, tetapi pada ketahanan jiwa saat menghadapi badai. Risa menyadari bahwa pendewasaan bukanlah proses yang manis, melainkan pembentukan karakter yang ditempa oleh api kesulitan.
Risa mungkin kehilangan sebagian dari kepolosan masa mudanya, tetapi ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih kokoh: kemandirian dan pemahaman mendalam tentang nilai sebuah warisan. Ia tidak lagi hanya melukis; ia sedang mengukir takdirnya sendiri.
Ketika akhirnya galeri itu berdiri tegak lagi, bukan karena keajaiban, melainkan karena keringat dan air matanya, Risa tahu ia telah melewati batas tak terlihat. Kedewasaan bukanlah tentang usia, melainkan tentang seberapa cepat kita bangkit saat dunia berusaha menjatuhkan kita ke lantai. Kini, ia menunggu babak apa lagi yang akan dituliskan pena takdir, dan ia siap menghadapinya.