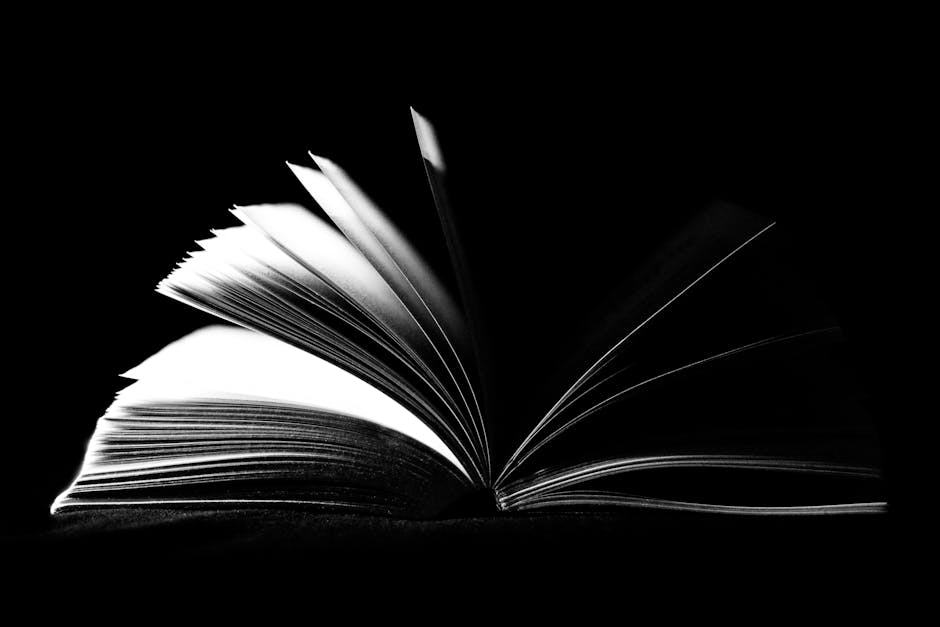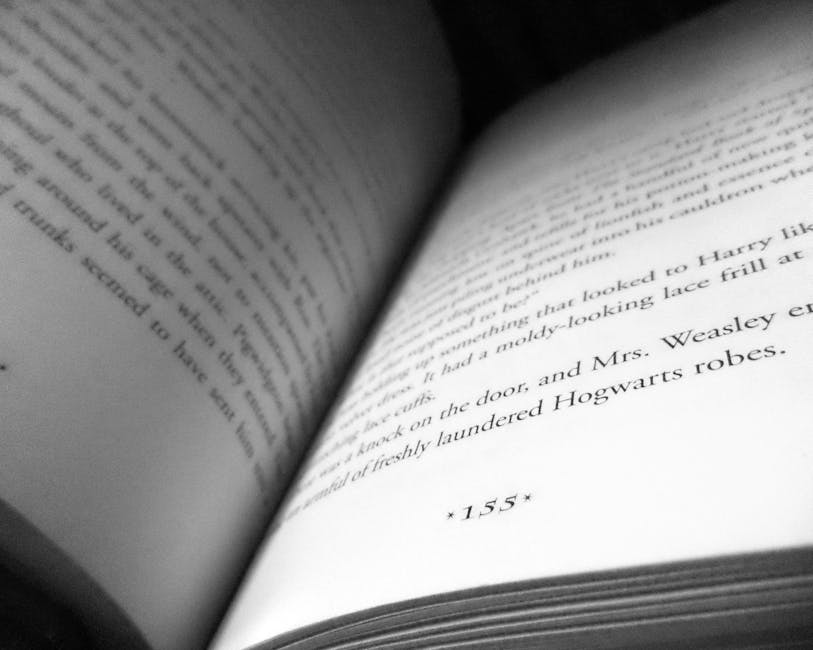Aku selalu berpikir bahwa masa depan adalah panggung megah, tempat aku akan memainkan melodi terbaikku. Sebagai putra tunggal yang dimanja, aku hidup dalam gelembung idealisme, percaya bahwa kesulitan hanyalah bumbu fiksi. Aku mencintai gitarku lebih dari apapun, mengabaikan kerutan cemas di dahi Ayah yang sibuk mengurus Bengkel Cahaya.
Dunia yang kukenal runtuh saat Ayah pergi mendadak. Bukan hanya duka yang menusuk, tetapi warisan pahit yang harus kuhadapi: tumpukan utang, laporan keuangan yang berantakan, dan karyawan yang menggantungkan hidup pada bengkel yang hampir mati. Gitar tiba-tiba terasa berat, dan nada-nada indahku tertutup oleh suara mesin yang rusak.
Aku marah pada takdir yang begitu kejam, yang merenggut panggungku dan melemparku ke tengah badai administrasi dan oli. Aku yang selalu bersih dan rapi, kini harus berkubang dalam debu dan keringat, mencoba memahami jargon-jargon teknis yang sama sekali tak kumengerti. Tidur hanya tiga jam sehari menjadi rutinitas baru, jauh dari studio rekaman impianku.
Setiap pagi, aku menatap papan nama Bengkel Cahaya, bertanya-tanya mengapa Ayah meninggalkanku beban seberat ini. Aku mencoba menjual aset, mencari jalan pintas, tetapi setiap upaya hanya menghasilkan kegagalan baru. Aku menyadari bahwa idealisme remajaku hanyalah ilusi; kedewasaan menuntut solusi, bukan sekadar harapan kosong.
Paman Bima, salah satu mekanik tertua, melihat kelelahan di mataku. Ia tidak memberiku uang, tetapi memberiku pelajaran tentang akar. Ia berkata, kekuatan sejati bukan pada seberapa keras kita memukul, melainkan pada seberapa gigih kita bangkit setelah dirobohkan. Beliau mengajarku bahwa kesabaran adalah mata uang yang paling berharga.
Perlahan, aku mulai menerima bahwa ini adalah babak terpenting dalam hidupku. Aku menyadari bahwa skenario pahit ini adalah bagian dari kurikulum yang disebut kedewasaan, sebuah pelajaran yang tidak pernah tercantum dalam buku kuliah. Inilah yang sesungguhnya dinamakan Novel kehidupan, di mana setiap air mata dan luka menjadi tinta yang membentuk karakterku.
Aku mulai mengambil keputusan sulit: merampingkan biaya, memberhentikan beberapa karyawan dengan berat hati, dan bahkan menjual sebagian koleksi gitarku demi melunasi utang kecil. Setiap keputusan terasa seperti pisau yang mengiris, tetapi rasa sakit itu membangun tembok ketahanan yang tak pernah kumiliki sebelumnya.
Tangan yang dulunya hanya terbiasa memetik senar kini mahir memegang kunci pas. Wajahku tak lagi semulus dulu, dihiasi noda oli yang sulit hilang, namun di sana terpancar ketenangan yang baru. Aku mungkin kehilangan waktu untuk bermusik, tetapi aku menemukan diriku yang sesungguhnya—seorang pemimpin, bukan lagi seorang pemimpi yang terlindungi.
Bengkel Cahaya memang belum kembali berjaya, tetapi napasnya kini stabil. Aku berhasil melunasi sebagian besar utang dan membalikkan keadaan dari jurang kebangkrutan. Namun, saat aku akhirnya bisa tersenyum lega, sebuah surat misterius tiba di meja kerjaku, surat yang berisi petunjuk tentang rahasia tersembunyi Ayah, sebuah rahasia yang jauh lebih besar daripada utang bengkel ini. Apakah kedewasaan yang baru kuperoleh cukup kuat untuk menghadapi kebenaran yang akan mengubah segalanya?