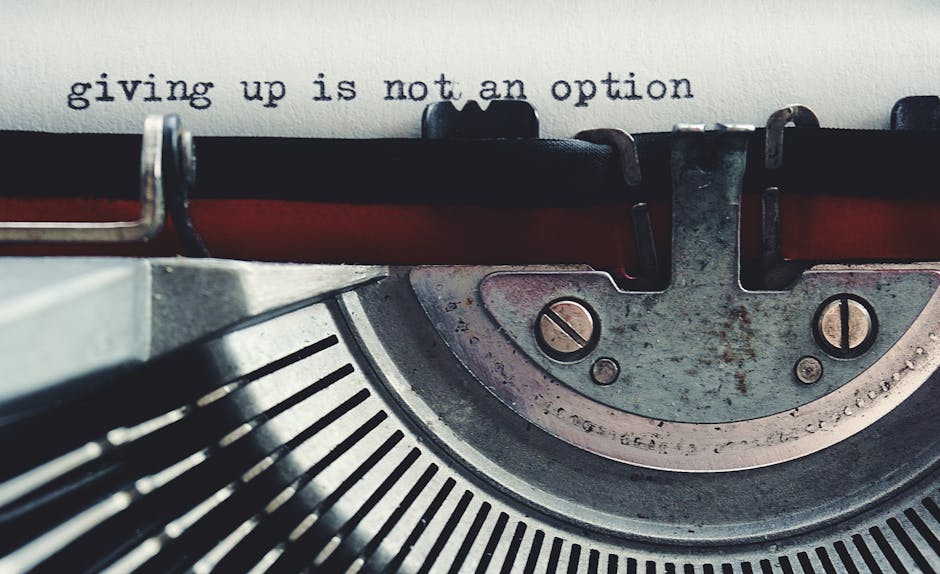Aku selalu percaya bahwa hidupku adalah sebuah jalan setapak yang mulus, berhiaskan bunga-bunga kemudahan yang ditanamkan oleh tangan orang tua. Kepercayaan itu luruh seketika, seperti istana pasir yang dihantam ombak besar, saat tiba-tiba aku harus menghadapi kekosongan yang ditinggalkan oleh kepergian mendadak Ayah. Aku dipaksa berdiri di tengah badai, tanpa peta, tanpa kompas.
Gegar yang kurasakan bukan hanya kehilangan sosok, tetapi juga hilangnya fondasi finansial dan emosional yang selama ini menopangku. Malam-malam yang biasanya dipenuhi tawa dan diskusi ringan kini berganti dengan keheningan mencekam, hanya ditemani suara detak jam yang terasa begitu lambat dan mengintimidasi. Aku harus mengambil alih peran, mencari cara agar dapur tetap mengepul.
Tiba-tiba, tugas yang dulu terasa remeh, seperti membayar tagihan atau berhadapan dengan birokrasi yang rumit, menjadi medan perang yang sesungguhnya. Aku sering menangis di balik pintu kamar mandi, merasa bodoh dan tak siap menghadapi realitas yang begitu keras dan tanpa kompromi. Keputusasaan sempat menjadi teman akrab, menawarkan pelarian yang terasa sangat menggoda.
Namun, di tengah titik terendah itu, sebuah kesadaran menghantamku: aku tidak bisa terus menjadi korban. Aku harus menjadi protagonis yang kuat dalam ceritaku sendiri. Ternyata, babak dalam novel kehidupan yang sesungguhnya tidak pernah ditulis dengan tinta emas kemudahan, melainkan diukir dengan darah dan keringat perjuangan yang tak terhindarkan.
Aku mulai bekerja, melakukan apa saja yang halal, dari mengajar privat hingga menjadi barista di kedai kopi. Rasa lelah fisik yang mendera justru menjadi pengalih perhatian dari rasa sakit emosional. Aku belajar menghargai setiap lembar rupiah yang didapatkan dengan susah payah, dan mulai memahami makna sebenarnya dari tanggung jawab.
Setiap penolakan, setiap kegagalan kecil dalam mengelola usaha, menjadi mata kuliah yang tak ternilai harganya. Aku belajar bahwa kedewasaan bukan hanya soal usia, melainkan tentang kemampuan untuk bangkit kembali setelah terjatuh, tanpa menyalahkan gravitasi atau nasib buruk.
Perlahan, pecahan diriku mulai tersusun kembali, tidak lagi sebagai cerminan masa lalu yang nyaman, tetapi sebagai mozaik baru yang lebih kuat. Aku melihat diriku yang baru—sosok yang lebih tangguh, lebih bijaksana, dan yang paling penting, sosok yang mampu memberikan perlindungan dan ketenangan bagi Ibu.
Pengalaman pahit itu adalah guru terhebat. Ia merenggut kepolosanku, tetapi sebagai gantinya, ia memberiku empati dan pemahaman mendalam tentang perjuangan orang lain. Aku tidak lagi takut pada kesulitan; aku justru menyambutnya, karena aku tahu setiap badai adalah kesempatan untuk menguji seberapa kokoh akarku.
Kedewasaan sejati adalah ketika kita menyadari bahwa kita bertanggung jawab atas kebahagiaan dan keselamatan diri sendiri. Jika suatu hari nanti badai kembali datang, aku tidak akan lari. Aku akan berdiri tegak, membiarkan angin membersihkan sisa-sisa keraguan, dan menunjukkan bahwa seorang anak manusia bisa tumbuh menjadi pohon yang rindang, bahkan dari tanah yang paling kering sekalipun.