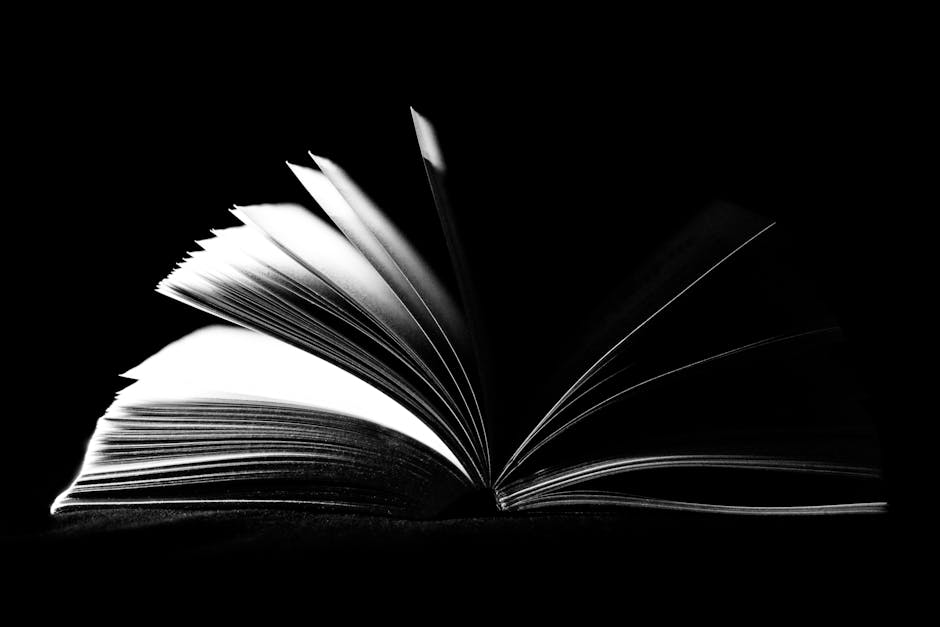Dulu, aku pikir kedewasaan adalah tentang mencapai gelar tertinggi atau merayakan ulang tahun ke-21 yang meriah. Risa, si gadis buku, hanya mengenal aroma kertas dan janji-janji masa depan yang mulus. Dunia bagiku hanyalah sebuah peta yang sudah digariskan, tanpa hambatan berarti.
Peta itu robek ketika panggilan telepon itu datang di tengah malam, membawa kabar buruk tentang kesehatan Ayah. Tabungan keluarga terkuras habis dalam sekejap mata untuk biaya pengobatan yang tak terduga. Aku harus melepaskan beasiswa impianku di luar negeri, menggantinya dengan kenyataan pahit mencari pekerjaan apa pun di ibu kota.
Risa yang biasanya hanya memegang pena kini harus mengangkat kotak-kotak berat di gudang logistik yang panas dan berdebu. Kaki pegal dan telapak tangan yang kapalan menjadi saksi bisu betapa jauhnya aku dari perpustakaan yang kukenal. Setiap malam, aku tertidur bukan karena bosan membaca, tapi karena kelelahan fisik yang tak tertahankan.
Di gudang itu, aku bertemu banyak wajah yang menyimpan kisah perjuangan yang jauh lebih berat daripada yang aku alami. Mereka adalah para ibu tunggal, para perantau yang gigih, yang mengajariku arti sabar dan syukur tanpa perlu ceramah. Aku mulai menyadari bahwa masalahku, betapapun menyakitkannya, bukanlah akhir dari segalanya.
Kedewasaan ternyata bukan sekadar angka, melainkan kemampuan untuk berdiri tegak saat badai menerpa orang-orang yang kita cintai. Aku mulai menulis kembali skenario hidupku, bukan sebagai korban, melainkan sebagai pemeran utama yang bertanggung jawab penuh. Inilah babak terpenting dalam Novel kehidupan yang sedang aku jalani.
Aku belajar membaca kode inventaris lebih cepat daripada membaca puisi, dan aku belajar mengorganisir stok lebih rapi daripada mengorganisir catatan kuliah. Pujian yang kudapatkan dari rekan kerja karena ketenangan dan efisiensiku terasa lebih berharga daripada nilai A tertinggi yang pernah kucapai. Aku menemukan kekuatan tersembunyi dalam diriku, kekuatan yang hanya muncul saat terdesak.
Mimpi lama masih ada, tersimpan rapi, namun kini ia memiliki fondasi yang lebih kuat, terbuat dari keringat dan ketahanan. Aku tidak lagi terburu-buru; aku menghargai setiap proses, setiap momen saat aku bisa mengirimkan uang untuk pengobatan Ayah. Pengalaman ini membentukku menjadi seseorang yang lebih tangguh, yang tidak takut kotor dan tidak takut gagal.
Kini, setelah Ayah membaik dan aku menabung cukup banyak, pintu universitas impian itu kembali terbuka. Aku berdiri di persimpangan jalan, membawa bekal yang jauh lebih berharga daripada sekadar kepintaran akademis. Pertanyaannya, apakah aku siap untuk babak selanjutnya, membawa jiwa gudang logistik yang keras dan empati yang mendalam ke dalam ruang kuliah yang hening?