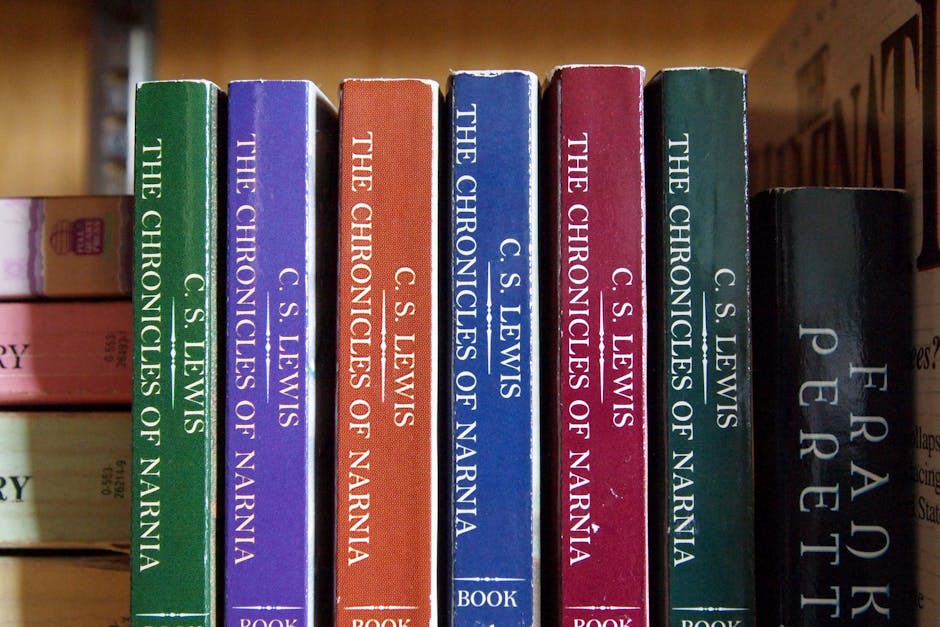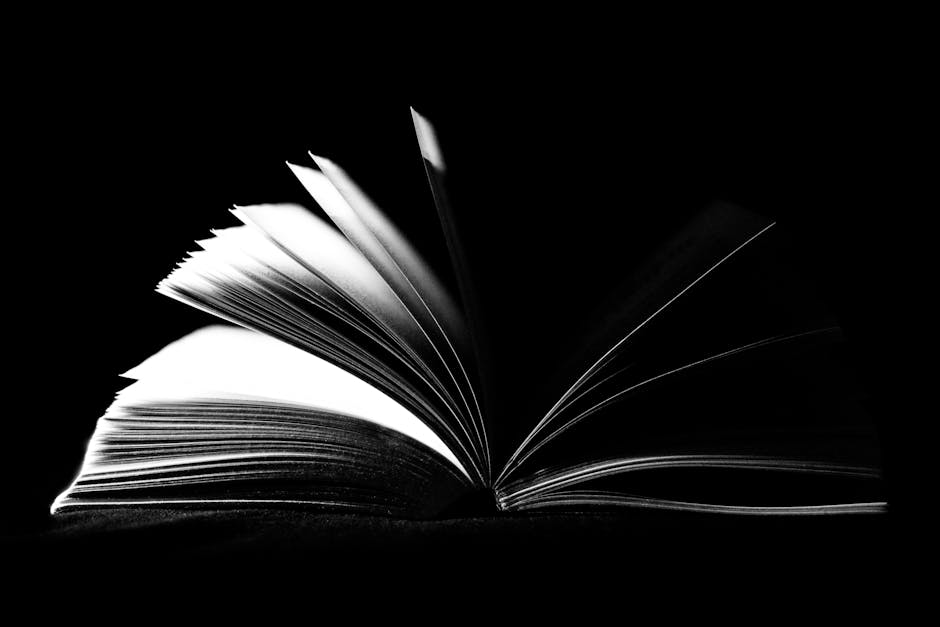Aku selalu percaya bahwa hidup adalah kanvas yang harus dilukis dengan kesempurnaan, tanpa cacat sedikit pun. Sebagai seorang perancang muda yang idealis, aku memeluk ambisi setinggi langit, yakin bahwa visi yang murni pasti akan disambut dengan tepuk tangan meriah. Namun, aku lupa bahwa langit juga menyimpan badai yang tak terduga.
Pukulan itu datang saat proyek pertamaku, yang kubangun dengan seluruh jiwa, runtuh di hadapan mata publik. Bukan hanya gagal, tapi hancur total, meninggalkan puing-puing kritik pedas dan rasa malu yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Dunia yang kukenal—dunia yang rapi dan terencana—tiba-tiba menjadi labirin yang gelap dan dingin.
Selama berminggu-minggu, aku hanya bisa bersembunyi di balik tirai kamar, membiarkan kebisingan dunia luar meredam suara hatiku sendiri. Aku mencari kambing hitam; menyalahkan tim yang tidak kompeten, klien yang tidak mengerti seni, bahkan takdir yang kejam. Jauh di lubuk hati, aku tahu ini adalah cara pengecut untuk menghindari cermin.
Suatu sore, Nyonya Wina, mentor lamaku, datang membawa sepotong kue dan senyum yang menenangkan. Ia tidak memberiku motivasi kosong, melainkan sebuah pertanyaan tajam: “Apakah kamu akan terus menjadi korban, Risa, atau kamu akan menjadi arsitek dari keruntuhan ini?” Pertanyaan itu menampar kesombonganku yang tersisa. Aku menyadari bahwa kedewasaan bukanlah tentang menghindari kesalahan, melainkan tentang kemampuan untuk berdiri tegak di tengah reruntuhan yang kita ciptakan sendiri. Tanggung jawab, ternyata, adalah bentuk keberanian yang paling sunyi.
Aku mulai membaca kembali semua laporan, semua email yang kubuang, mencari celah yang selama ini kutolak untuk lihat. Aku menemukan jejak-jejak ketidakpedulianku, detail-detail kecil yang kusepelekan karena terlalu fokus pada gambaran besar yang sempurna. Inilah babak terberat dalam Novel kehidupan yang harus kutulis.
Menerima kegagalan itu seperti menerima bekas luka bakar; rasa sakitnya nyata, tapi ia meninggalkan kulit baru yang lebih kuat. Aku mengirim surat permintaan maaf yang tulus kepada semua pihak yang dirugikan, bukan untuk memulihkan reputasiku, tetapi untuk memulihkan integritasku.
Proses pemulihan ini mengajarkanku bahwa kedewasaan sejati tidak diukur dari seberapa banyak kesuksesan yang kita raih, melainkan dari seberapa cepat kita bangkit setelah terhempas. Bekas luka itu kini menjadi kompas, mengingatkanku bahwa idealisme harus selalu dibalut dengan kerendahan hati dan ketelitian.
Sekarang, aku kembali bekerja, bukan lagi mengejar kesempurnaan yang mustahil, tetapi merangkul proses yang berantakan. Aku tahu badai lain pasti akan datang, tetapi kali ini, aku tidak akan lari. Aku akan berdiri, siap memegang pena untuk menulis babak selanjutnya. Apakah aku akhirnya benar-benar dewasa? Atau ini baru permulaan dari ujian yang lebih besar?